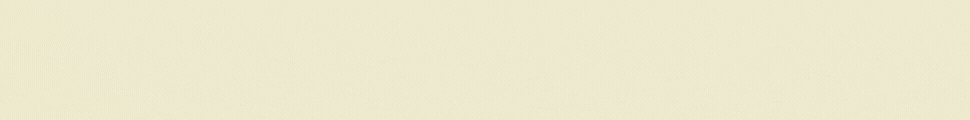“Semua karakter, peristiwa, dan lokasi dalam kisah ini adalah fiksi dan tidak memiliki hubungan dengan kejadian nyata. Penulis berharap pembaca menikmati kisah ini sebagai hiburan semata dan tidak menganggapnya sebagai fakta sejarah.”
Bab 8: Niat Jahanam Murid Durhaka
Di dalam sebuah pondok kecil yang tersembunyi di tengah hutan lebat, dua sosok duduk berhadapan. Lampu minyak yang tergantung di atas mereka memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan panjang dan misterius di dinding bambu.
Saung Galing menatap Pratiwi dengan wajah memerah, tangannya mengepal erat. “Tidak mungkin, Pratiwi! Kita tidak mungkin membunuh guru!” suaranya menggelegar, memecah keheningan hutan yang menyelimuti mereka.
Pratiwi, perempuan berwajah tirus dengan riasan mencolok, hanya tersenyum sinis. “Apa kakang akan terus diam saja, meski tahu siapa pembunuh ayahandamu?” Nada suaranya pelan, tapi tajam seperti bilah belati.
Saung Galing terdiam. Dada bidangnya naik turun, dadanya bergemuruh dalam dilema. Bara amarah dalam hatinya mulai menyala, tapi masih tertahan oleh sisa-sisa keraguan.
Pratiwi melanjutkan dengan suara berbisik, “Ini kesempatan kita. Guru sedang lemah. Aku, kakang, dan kakang Mahesa… jika kita bekerja sama, aku yakin kita bisa menumbangkannya!”
Intan Pratiwi—murid ketiga Ki Jaga Baya—adalah perempuan ambisius yang merasa dikhianati. Hatinya membara saat Ki Jaga Baya tidak memilihnya sebagai pewaris Cincin Genta Buana.
Dari luar pondok, suara serangga malam terdengar semakin nyaring, seolah turut menjadi saksi bisu percakapan gelap itu. Angin dingin menyusup di antara celah-celah dinding bambu, menggoyangkan dedaunan di luar, seolah ikut berbisik mengintai niat jahat mereka.
Saung Galing bangkit berdiri, tubuh gempalnya tegang. Wajahnya yang keras tampak diliputi pertarungan batin. Beberapa kali ia menarik napas dalam-dalam, seakan mencoba menenangkan badai di dadanya.
“Kakang bingung, Pratiwi,” desahnya berat. “Satu sisi, guru adalah orang yang merawat dan mengasuhku sejak kecil. Tapi di sisi lain… dia adalah pembunuh orang tuaku! Kakang benar-benar bingung…”
Pratiwi mendekat, menatapnya dengan sorot penuh kelicikan. “Sudahlah, kakang. Guru merawatmu hanya agar kau tak menuntut balas. Itu caranya mengikatmu dalam utang budi. Tapi kau tak bisa lari dari kenyataan. Aku sendiri mendengar dengan telinga ini, bagaimana ayahandamu dibunuh olehnya tanpa alasan!”
Saung Galing mengalihkan pandangannya, giginya bergemeletuk menahan emosi. “Baik,” katanya akhirnya, “Lalu bagaimana caranya? Meski dibantu kakang Mahesa, kita belum tentu mampu menghadapinya.”
Pratiwi tersenyum puas. Dari balik selendangnya, ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hitam pekat, terbungkus anyaman lontar tebal. Ia meletakkannya di atas meja dengan hati-hati.
“Inilah caranya,” bisiknya. “Racun Kelabang Geni. Aku mendapatkannya dari Nyai Kelabang Geni sendiri. Satu tetes saja cukup untuk melumpuhkan harimau.”
Saung Galing menatap botol itu dengan ekspresi bercampur aduk—ragu, marah, dan terperangkap dalam pusaran dendam.
Sementara itu, di dalam hatinya, Pratiwi membatin dengan penuh kebencian.
“Kesalahanmu, tua bangka Jaga Baya! Engkau pilih kasih. Aku murid yang lebih tua, tapi mengapa Mayang Sari yang kau angkat sebagai pewaris Cincin Genta Buana?!”
*****
Bidadari Berselendang Emas
Seorang wanita cantik berpakaian kuning keemasan memacu kuda tunggangannya dengan kecepatan penuh. Selendang sutera emas yang melilit tubuhnya berkibar tertiup angin, mengikuti gerakan lincah kuda coklat tua yang berpacu di jalan berdebu.
“Hiyaaa! Hiyaaa! Lebih cepat, Lana!” serunya, menepuk leher kuda kesayangannya, Kudalana.
Debu berterbangan di udara, tetapi wanita itu tak peduli. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Ia baru saja melihat penglihatan dari Cincin Genta Buana, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir ketakutan.
“Aku harus tiba sebelum semuanya terlambat! Guru… aku harus menyelamatkan guru!” gumamnya dalam hati.
Dialah Ratu Mayangsari, murid kesayangan Ki Jaga Baya—sang Bidadari Berselendang Emas.
Sementara itu, di tempat lain…
Di dalam sebuah pondok tua yang dikepung pepohonan lebat, tiga murid Ki Jaga Baya tengah tenggelam dalam perdebatan panas. Mahesa Rana, murid tertua, mencoba menahan adik-adiknya agar tak terjerumus dalam rencana pengkhianatan.
“Tidak, Adi Pratiwi, Adi Saung Galing!” suara Mahesa Rana bergetar. “Ini bukan jalan yang benar! Membunuh guru sendiri… itu bukanlah kehormatan seorang pendekar!”
Namun, Intan Pratiwi hanya tersenyum sinis.
“Kakang terlalu naif,” katanya, nada suaranya licik. “Guru itu tidak pernah menganggap kita! Baginya hanya Mayang Sari yang berharga! Kakang harus sadar, inilah saatnya kita menyingkirkannya!”
“Iya, kakang!” timpal Saung Galing, matanya menyala penuh dendam. “Tua bangka itu bukan malaikat! Dia iblis yang membunuh ayahandaku! Aku harus membalasnya!”
Mahesa Rana menggertakkan gigi. Hatinya terombang-ambing antara kesetiaan dan kekecewaan.
“Aku… aku masih ragu… Apakah ini keputusan yang terbaik?” tanyanya lirih.
Saung Galing mendekat, menatapnya dengan tajam. “Kakang, apa kakang tidak sakit hati? Guru membiarkan Mayang Sari dipersunting orang lain, padahal kakang sangat mencintainya!”
Mahesa Rana terhenyak. Perasaannya yang selama ini ia pendam, tiba-tiba mencuat ke permukaan.
“Dan jangan lupa, kakang…” suara Intan Pratiwi makin lembut, namun beracun. “Setelah Jaga Baya mati, Cimeti Bondoyono dan Kitab Tapak Naga Samudera akan menjadi milikmu, dan perguruan ini akan menjadi milikmu…”
Intan Pratiwi melangkah mendekat, tangannya mengusap perutnya perlahan. “Satu lagi, kakang… Aku akan mendampingimu hingga tua. Dan… kita akan membesarkan janin yang ada dalam kandunganku ini…”
Mahesa Rana tersentak. Wajahnya mendadak pucat.
“Adi Pratiwi, hentikan ucapanmu!” katanya tajam. “Soal itu… jangan diumbar sembarangan. Aku sudah berjanji… dan aku pasti akan bertanggung jawab atasmu!”
Namun, Pratiwi hanya tersenyum licik. “Tapi, kakang… Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang masa depan. Tentang guru yang harus kita singkirkan…”
Mahesa Rana mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Pikirannya berkecamuk.
Hening menyelimuti pondok itu. Hanya suara angin yang berdesir, menggoyangkan dedaunan di luar, seolah turut menjadi saksi atas niat jahat yang semakin matang di dalam hati mereka.
*****
Racun Kelabang Geni
Di dalam sebuah gua yang hanya diterangi lampu tempel, nyala apinya meliuk-liuk mengikuti hembusan angin malam. Bayangan-bayangan bergerak di dinding batu, seakan menari dalam irama sunyi.
Di tengah gua itu, duduk seorang lelaki tua berjubah putih dengan janggut panjang yang menjuntai hingga dada. Wajahnya memancarkan kewibawaan, sorot matanya teduh namun penuh ketegasan. Dialah Ki Jaga Baya—sang Pendekar Tapak Naga Samudera, sosok yang disegani seantero Swarna Dwipa.
Bagi mereka yang pernah ditolongnya, Ki Jaga Baya adalah pahlawan. Namun, bagi para pendekar golongan hitam, namanya adalah momok yang menakutkan. Tangannya telah merenggut nyawa banyak perampok, penjahat, dan pendekar sesat yang mencoba menebar kejahatan.
Tiba-tiba, suara pelan penuh hormat terdengar di telinganya.
“Guru, kami mohon maaf telah mengganggu semedi guru, tapi ada hal penting yang harus kami sampaikan…”
Ki Jaga Baya membuka matanya perlahan, tatapannya tetap tenang.
“Nyai Kelabang Geni dan pengikutnya sedang menuju ke tempat ini untuk balas dendam! Kami bertiga belum tentu mampu melawannya, guru…”
Ki Jaga Baya menghela napas dan menggeser sedikit tubuhnya. Suaranya dalam dan tenang saat menjawab, “Masuklah. Katakan dengan lebih jelas.”
Tiga muridnya segera melangkah masuk, lalu bersimpuh di hadapan sang guru. Mahesa Rana, murid tertua, mengenakan pakaian putih dengan ikat kepala hitam, raut wajahnya tegang. Saung Galing, pria bertubuh gempal dengan pakaian abu-abu, tampak gelisah. Intan Pratiwi, satu-satunya murid perempuan, berusaha menampilkan ketakutan di wajahnya—walau ada sesuatu yang tersembunyi di balik sorot matanya.
“Mereka sudah tidak jauh lagi, guru,” kata Mahesa Rana dengan nada serius. “Apa yang harus kami lakukan? Guru masih dalam semedi…”
Ki Jaga Baya menatap murid-muridnya satu per satu. “Tenanglah, Mahesa… Saung… dan kamu, Intan. Aku tidak akan tinggal diam jika keangkaramurkaan mengancam. Aku telah mengabdikan hidupku untuk menegakkan kebenaran. Selama aku masih bernapas, padepokan ini tidak akan jatuh ke tangan Nyai Kelabang Geni!”
Suasana di dalam gua mendadak hening.
Tiba-tiba, Intan Pratiwi tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik selendangnya. Ia meletakkan sebuah klongsong bambu berisi minuman hangat di hadapan Ki Jaga Baya.
“Guru,” ujarnya lembut. “Sebelum ke sini, aku sudah menyiapkan minuman kesukaan guru. Wedang jahe dengan gula aren…”
Tangannya menyentuh bambu itu dengan penuh kelembutan.
“Minumlah selagi masih panas, guru. Ini akan menghangatkan tubuh dan menyegarkan pikiran.”
Saung Galing menatapnya sekilas, lalu menunduk. Mahesa Rana mengusap keningnya yang basah oleh keringat.
Ki Jaga Baya mengelus janggutnya yang panjang, lalu tersenyum.
“Terima kasih, Intan…” katanya dengan suara tenang. “Kamu memang paling tahu kesukaanku…”
Tak ada yang menyadari, dalam tatapan mata Intan Pratiwi terselip sinar berbahaya.
Tanpa ragu dan curiga, Ki Jaga Baya mengambil klongsong itu dan membuka penutupnya. Dia memang sangat menyukai minuman wedang jahe yang ditambah gula aren.
Aroma hangatnya segera menguar, memberikan sensasi menenangkan yang sejenak membuatnya lupa akan kelelahan setelah seharian berlatih dengan para muridnya.
Namun, di sisi lain, suasana di sekitar meja menjadi berbeda. Mahesa Rana, Saung Galing, dan Intan Pratiwi saling melempar pandang dengan raut wajah tegang.
Mereka tahu betul, satu kesalahan kecil saja akan mengantarkan mereka pada kematian. Jika Ki Jaga Baya menyadari ada yang tidak beres dengan wedang jahe itu, maka mereka bertiga tidak akan pernah bisa lolos dari tangan guru mereka.
Gluk… gluk… gluk…
Cairan berwarna coklat tua itu mengalir dari klongsong ke dalam mulut Ki Jaga Baya. Bau harum jahe bercampur gula aren memenuhi ruangan. Ia menyesapnya perlahan, menikmati sensasi hangat yang menjalar ke tenggorokannya.
Namun, hanya dalam sekejap, mata Ki Jaga Baya terbelalak. Napasnya tersengal. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya. Dadanya terasa panas membakar, seolah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk dari dalam.
Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ia mengedarkan pandangan ke arah murid-muridnya. “Apa yang kalian campurkan pada minuman ini?” suaranya menggema, penuh amarah dan kekecewaan.
Darah segar berwarna kehitaman menyembur dari mulut lelaki tua itu. Tangannya mencengkeram dadanya, mencoba menyalurkan tenaga dalam untuk melawan racun yang mulai menggerogoti tubuhnya.
Pandangannya kabur, namun ia masih bisa menangkap ekspresi gugup dari ketiga muridnya.
“Kalian… kalian…” ucapnya terputus-putus.
Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tombak panjang tiba-tiba menujam tepat ke perutnya. Saung Galing, dengan wajah penuh kebencian, menusukkan senjatanya dengan brutal.
“Akhaa…kalian…kalian…” Ki Jaga Baya terhuyung ke belakang, kedua tangannya berusaha menahan luka parah yang terus mengeluarkan darah segar.
Saung Galing justru tertawa penuh dendam. “Rasakan ini, iblis! Ini adalah balasan atas kematian ayahandaku yang kau bunuh!” teriaknya, lalu kembali menghujamkan tombak dengan kejam.
Di sisi lain, Intan Pratiwi tak tinggal diam. Wanita licik itu dengan cepat melayangkan tiga senjata rahasia berbentuk jarum yang telah dilumuri racun Kelabang Geni ke arah tubuh Ki Jaga Baya. Jarum-jarum itu melesat dengan kecepatan tinggi dan menancap tepat di bahunya.
Sementara itu, Mahesa Rana hanya terpaku. Tangannya bergetar, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ia menyaksikan bagaimana dua adik seperguruannya menyerang guru mereka tanpa ampun.
“A…a…a… aku tidak tega, Saung! Intan! Hentikan! Dia guru kita!” suara Mahesa Rana terdengar lirih, hampir tidak terdengar di tengah hiruk-pikuk keheningan yang mencekam.
“Tidak, Kakang! Sudah terlanjur! Dendam ini harus terbayarkan!” sahut Saung Galing dengan mata merah dipenuhi kebencian.
Tombaknya kembali menghunjam tubuh Ki Jaga Baya yang semakin melemah. Darah segar bercipratan ke lantai, membentuk genangan pekat yang menghitam.
Mahesa Rana akhirnya bergerak, mencoba menahan tangan Saung Galing. “Sudah, hentikan! Guru sudah tewas!” suaranya bergetar. Ia menunjuk tubuh Ki Jaga Baya yang telah kaku, wajahnya membiru, tubuhnya dipenuhi luka, dan darah masih terus mengalir membasahi jubah putihnya.
Namun, di balik tubuh yang tak lagi bergerak itu, mata Ki Jaga Baya yang mulai kehilangan cahaya masih menatap mereka. Tatapan itu… bukan tatapan seorang yang menyerah, melainkan tatapan yang menyimpan sesuatu yang tak terduga…
Di tengah gua yang kini sunyi, Saung Galing, Intan Pratiwi, dan Mahesa Rana menatap tubuh Ki Jaga Baya yang terbujur kaku. Darah menghitam membasahi lantai batu. Wajah lelaki tua itu masih memancarkan ketenangan, meskipun telah dikhianati murid-muridnya sendiri.
Intan Pratiwi menyeringai puas. “Akhirnya… kita bebas dari bayang-bayangnya!” serunya sambil meraih tangan Saung Galing. “Sekarang, perguruan ini akan menjadi milik kita!”
Namun, Mahesa Rana masih diam. Dadanya sesak, pikirannya berperang. “Apa benar ini yang seharusnya terjadi?” gumamnya.
Belum sempat ia merenung lebih jauh, tiba-tiba angin dingin berembus kuat di dalam gua. Api lampu tempel bergetar hebat, hampir padam. Aroma dupa dan bunga setaman memenuhi udara.
Dari bayangan yang merayap di dinding gua, suara berat menggema, “Kalian mengira telah menyingkirkanku?”
Saung Galing tersentak. “Siapa itu?! Guru?!”
Bayangan menyerupai Ki Jaga Baya muncul perlahan. Matanya bersinar redup, tapi penuh kekuatan. “Tubuh ini memang telah kau hancurkan… tapi aku masih ada!”
Intan Pratiwi mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. “Itu tidak mungkin! Racun Kelabang Geni tak pernah gagal!”
Dari sudut gua, dua sosok harimau hitam, Kurnala dan Kumbala, melangkah ke depan. Mata mereka bersinar tajam, seolah menatap langsung ke dalam hati para murid durhaka itu.
Mahesa Rana menelan ludah. “Ini… ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal.”
Bayangan Ki Jaga Baya perlahan menoleh ke arah mereka. “Aku telah mempercayai kalian, mengajarkan ilmu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Tapi kalian memilih jalan kegelapan.”
Saung Galing berteriak, mencoba menutupi ketakutannya dengan amarah. “Aku tidak menyesal! Aku akan menggenggam kekuatan ini dengan tanganku sendiri!”
Ki Jaga Baya tersenyum tipis. “Kita lihat… siapa yang benar-benar layak menggenggam takdir ini.”
Seketika, angin kencang berputar di dalam gua. Suara-suara gaib bergema. Kurnala dan Kumbala mengaum keras, lalu lenyap bersama bayangan Ki Jaga Baya.
Mahesa Rana menggigil. Intan Pratiwi terjatuh, tubuhnya lemas. Sementara Saung Galing hanya bisa mengepalkan tinjunya—ia tahu, ini belum berakhir.
Di tempat lain, Ratu Mayangsari masih memacu Kudalana secepat angin. Matanya tajam, hatinya dipenuhi tekad. “Guru… bertahanlah! Aku akan segera datang!”
Ratu Mayangsari menatap nanar tubuh gurunya yang telah membisu. Tangannya yang gemetar menyentuh wajah Ki Jaga Baya yang mulai dingin. Air matanya jatuh membasahi dada lelaki tua yang semasa hidupnya adalah panutan dan benteng kebaikan.
“Guru… siapa yang melakukan ini?!” suaranya bergetar, diiringi isak tangis yang tertahan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia telah tahu jawabannya. Cincin Genta Buana yang melingkar di jarinya masih memancarkan cahaya samar, menunjukkan kilasan peristiwa yang baru saja terjadi.
Mahesa Rana, Saung Galing, dan Intan Pratiwi—tiga murid durhaka yang telah mengkhianati sumpah mereka.
Kemarahannya berkobar. Selendang emas yang melilit tubuhnya mulai berpendar, menandakan tenaga dalamnya yang telah mencapai puncak. “Kakak-kakakku… kalian akan menyesali perbuatan ini!” desisnya, suara yang dulu lembut kini mengandung bara dendam yang menyala-nyala.
Namun, sebelum dia bisa melangkah keluar dari gua, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Ki Jaga Baya yang terbujur kaku mendadak bersinar.
Dari bayang-bayang gua, muncul dua sosok yang dikenalnya dengan baik—Kurnala dan Kumbala, dua harimau hitam penjaga Padepokan Tapak Naga Samudera. Mata mereka yang tajam menatap Mayangsari dengan sorot penuh makna.
“Ratu Mayangsari, tangisanmu takkan membangkitkan jasad gurumu,” suara Kurnala bergema. “Namun, dengarkan baik-baik. Guru telah menitipkan sebuah pesan sebelum ajal menjemputnya.”
Mayangsari menahan napas. Dia tahu, ini bukan sekadar pesan biasa.
“Cemeti Bondoyono dan Kitab Tapak Naga Samudera kini berada dalam perlindungan kami,” lanjut Kumbala. “Hanya seorang yang ditakdirkan yang bisa memilikinya. Orang itu bukan kami, bukan pula dirimu, tetapi seorang pemuda yang akan datang di masa depan.”
Mayangsari terdiam. Pemuda di masa depan? Siapa? Apa mungkin… seseorang yang akan membawa perubahan besar?
“Untuk saat ini, tugasmu adalah menegakkan kebenaran. Namun ingat, dendam takkan membawa kedamaian. Pilihlah jalanmu dengan bijak, wahai Bidadari Berselendang Emas,” ujar Kurnala sebelum keduanya menghilang dalam bayangan.
Mayangsari mengepalkan tangan. Api kemarahan masih berkobar, tetapi kini bercampur dengan kebingungan dan keraguan. Akankah dia memilih jalan balas dendam? Ataukah dia akan mencari kebenaran yang sesungguhnya?
Di kejauhan, angin berembus kencang. Langit kelam menyelimuti langit Swarna Dwipa. Ini bukan akhir… melainkan awal dari perang besar yang akan mengguncang tanah leluhur. Nantikan kelanjutan kisah Petualangan Sagara Sang Panglima Samudera di Bab 9 : Dilema Sari Patih.
[poll id=”2″]
Dukung Konten Berkualitas
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.
Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.