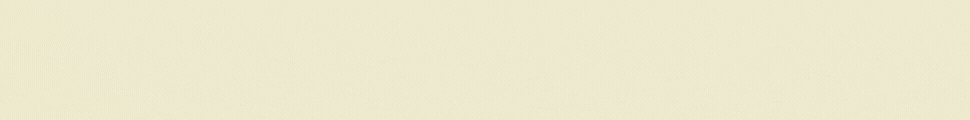Mentari pagi baru saja menyembul dari balik cakrawala, menyinari hamparan laut yang tenang di Pulau Panggang. Cahaya keemasan memantul di permukaan air, menyorot siluet perahu-perahu nelayan yang bersandar di dermaga kayu. Angin membawa aroma khas laut, bercampur dengan asap kayu dari dapur-dapur rumah panggung yang berjajar di tepi pantai.
Di antara deretan perahu, seorang pria berkulit legam dengan tubuh kekar tengah menarik jaring dari geladak perahunya yang usang. Muksin, nelayan berusia empat puluhan dengan rahang kokoh dan mata yang selalu tampak cemas, menatap hasil tangkapannya dengan wajah kecut. Hanya beberapa ekor ikan kecil dan seekor kakap yang berhasil ia dapatkan setelah semalaman di tengah laut.
Di dekatnya, Fadli—pria bertubuh tegap dengan kumis tebal dan sorot mata tajam—sedang mencuci perahunya dengan ember kecil. Ramli, lelaki bertubuh gempal dengan wajah bundar dan sering terlihat ceria, hari ini tampak muram. Ia duduk di atas geladak perahunya, menatap kosong ke arah laut.
“Laut makin pelit, Muk,” keluh Ramli, melempar batu kecil ke air.
“Bukan lautnya yang pelit, tapi kita yang makin susah cari ikan,” Fadli menimpali. Ia menyeka keringat di dahinya, menatap laut yang semakin jauh dari jangkauan mereka. “Dulu, di sekitar pulau ini aja ikan berlimpah. Sekarang? Harus jauh ke tengah, itu pun belum tentu dapat!”
Muksin menghela napas panjang. “Dan lihat harga solar sekarang,” gumamnya sambil melirik tangki bensin kecil di perahunya. “Satu liter mahalnya minta ampun. Kita harus bolak-balik ke darat beli es buat nyimpen ikan. Belum lagi beras, minyak, semuanya naik di bulan puasa ini.”
Si Nyinyir dan Sang Tengkulak
Dari arah warung kopi dekat dermaga, terdengar suara terkekeh. Nasir, pria bertubuh kurus dengan wajah tirus dan sering bersikap nyinyir, duduk santai sambil menyesap kopi dari gelas kaleng. Ia dikenal sebagai penjual solar eceran di Pulau Panggang, selalu punya stok, tapi menjualnya dengan harga lebih tinggi dari seharusnya.
“Halah, kalian ini nelayan kok sukanya ngeluh aja. Susah cari ikan, mahal beli solar… ya kalau susah, berhenti aja jadi nelayan!” katanya, dengan senyum sinis yang selalu mengundang amarah.
Muksin menoleh tajam. “Gampang ngomong kalau kerjaanmu cuma jualan solar. Kami yang harus ngelaut, risiko besar, hasil nggak seberapa.”
Nasir mengangkat bahu, masih dengan senyum mengejek. “Risiko besar? Cuma karena ikan lagi susah? Ayolah, Muk. Laut tetap di situ, yang berubah itu orangnya. Atau jangan-jangan kalian kalah saing sama kapal besar?”
Tiba-tiba, tawa keras terdengar dari ujung dermaga. Darus, pria bertubuh besar dengan wajah licik dan tangan penuh cincin emas, berdiri di atas perahu besar dengan lambung besi yang mencolok. Senyumnya lebar, tapi ada aura menekan di balik tatapannya.
“Muk, Muk… masih ngeluh juga?” katanya dengan nada mengejek. “Gimana mau untung kalau kalian nelayan kecil nggak mau berkembang? Masih pakai alat tangkap jadul, masih pakai cara lama. Wajar kalau kalah saing.”
Fadli mengepalkan tangan, matanya menatap Darus penuh kemarahan. “Kita bukan masalah kalah saing, Dar. Masalahnya lo dan kapal lo itu rakus! Pukat harimau lo bikin ikan makin susah! Yang kecil juga ikut keseret!”
Darus hanya tertawa, tangannya memainkan cincin di jarinya. “Laut itu buat siapa yang kuat, bukan buat yang banyak ngomong.”
Di belakang mereka, ibu-ibu nelayan tampak sibuk mengurus hasil tangkapan yang sedikit. Beberapa dari mereka memisahkan ikan kecil untuk dikeringkan, sementara yang lain menimbang ikan untuk dijual ke darat. Suara anak-anak berlarian di sekitar rumah panggung, menambah nuansa kehidupan di pulau kecil itu.
Harapan dari Daratan
Siang itu, Komarudin, seorang petugas dari pemerintah daerah, datang ke Pulau Panggang dengan mengenakan seragam khaki. Ia didampingi Halimah dan Nurlela, dua perempuan dengan wajah bersahaja yang bertugas di bidang pemberdayaan masyarakat nelayan.
“Bapak-bapak semua, kami paham kondisi kalian. Laut makin sepi, harga BBM naik, kebutuhan hidup makin mahal,” kata Komarudin di depan balai desa. “Itulah kenapa kami sedang berupaya mencari solusi.”
“Solusi?” potong Ramli dengan wajah kesal. “Dari dulu solusi cuma janji. Yang kami butuhkan itu kepastian! Nelayan kecil makin terjepit, tapi kapal besar kayak Darus makin berjaya!”
Komarudin menatap Ramli dengan sabar. “Kami bukan cuma datang untuk bicara. Ada program bantuan BBM bersubsidi yang sedang diperjuangkan untuk nelayan kecil seperti kalian. Selain itu, ada pelatihan alat tangkap ramah lingkungan yang bisa membantu meningkatkan hasil tangkapan.”
Halimah dan Nurlela menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menggencarkan pasar ikan murah, agar nelayan tak lagi terlalu bergantung pada tengkulak seperti Darus.
Tiba-tiba, suasana menjadi hening ketika seseorang melangkah ke depan. Adi Sulyono, teman lama mereka yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi di Kepulauan Seribu, berdiri dengan raut wajah serius.
“Saya ada di sini bukan cuma sebagai pejabat, tapi juga sebagai teman lama kalian,” katanya, matanya menatap Muksin, Fadli, Ramli, dan Nasir satu per satu. “Saya tahu perjuangan nelayan kecil, dan saya ingin pastikan kalian tidak sendirian dalam menghadapi ini.”
Muksin menatap Adi dengan tatapan penuh tanya. “Janji politis atau beneran mau bantu?”
Adi menghela napas. “Aku tahu kalian skeptis. Tapi kasih aku kesempatan. Aku akan buktikan kalau kita bisa perbaiki keadaan.”
Semua mata tertuju pada Adi. Apakah kali ini pemerintah benar-benar akan membantu mereka? Ataukah ini hanya janji kosong yang lain?
Muksin mengepalkan tangan, menatap laut yang semakin jauh dari harapan mereka. Ini bukan sekadar tentang ikan, bukan sekadar tentang harga. Ini adalah pertarungan nelayan kecil melawan gelombang ketidakadilan yang terus menghantam mereka.
To be continued…
Lima sekawan yang tergabung dalam Panca Wakun tumbuh bersama di pesisir, berbagi tawa, cita-cita, dan gelombang kehidupan. Kini, persahabatan mereka diuji oleh kerasnya laut dan ketidakadilan yang mengintai.
Dukung Konten Berkualitas
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.
Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.