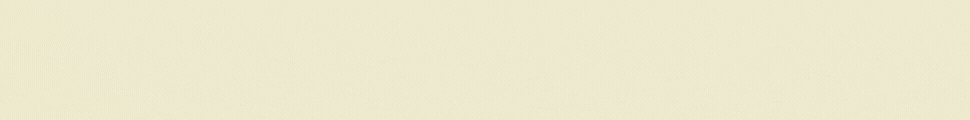Hujan turun deras malam itu. Gemuruh petir sesekali menyambar, menciptakan bayangan suram di dinding rumah. Ning duduk di ruang tamu, memeluk dirinya sendiri, sementara pikirannya melayang jauh.
Sudah berjam-jam sejak Kinan pergi mencari Kinanti. Dan kini, hanya suara hujan yang menemani kesepiannya.
Di atas meja, ponselnya tergeletak dengan layar menyala—deretan panggilan tak terjawab dan pesan yang belum mendapat balasan. Hatinya semakin gelisah.
“Ya Tuhan, Nanti anakku dimana?”
Hati seorang ibu tak pernah bisa benar-benar tenang ketika anaknya menghilang. Dan malam itu, ketakutan terbesarnya mulai menjadi nyata.
*****
Ning 5: Tuhan, Nanti Dimana?
Ning memeluk lututnya erat, tubuhnya gemetar. Kepalanya tertunduk, dan perlahan, isak tangis pecah dari bibirnya. Hujan deras mengguyur bumi di luar sana, menambah kesuraman malam itu. Kilatan petir sesekali menerangi ruangan, menciptakan bayangan-bayangan di dinding yang seolah menari dengan kecemasannya.
Di sampingnya, Kinan terduduk diam di lantai. Pandangannya kosong, pikirannya berkecamuk. Mereka berdua hanyut dalam kesedihan dan ketakutan, tak tahu harus berbuat apa.
“Kinanti… kemana kamu, Nak?” suara Ning bergetar, hampir tenggelam dalam suara hujan. “Bunda takut… Bunda khawatir banget sama kamu. Cepat pulang, ya?”
Dia menengadahkan wajah, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin dingin dan jauh. Air matanya mengalir deras, membasahi pipinya. Dalam keputusasaan, dia berbisik, “Tolong jaga Kinanti, Tuhan. Bantu kami menemukannya dengan selamat…”
Tangannya mengepal di dadanya, mencoba menahan ketakutan yang terus mencengkram. Lalu, sebuah pikiran buruk melintas. Ning menggigit bibirnya. “Kinan…,” suaranya nyaris tak terdengar. “Jangan-jangan ini ada hubungannya sama pekerjaanmu?”
Bayangan mengerikan mulai memenuhi kepalanya. Dia membayangkan Kinanti diculik, disiksa, bahkan—tidak! Ning menggeleng cepat, menolak membiarkan pikirannya melangkah lebih jauh. Namun, rasa takut itu terus merayapi hatinya, membuatnya nyaris sesak.
“Kita harus cepat cari Kinanti, Kinan,” Ning menatap suaminya, suaranya kini penuh kepanikan. “Aku takut terjadi sesuatu sama dia…”
Dengan sisa tenaga, Ning bangkit dari duduknya. Matanya yang sembab memantulkan tekad yang goyah, tapi dia tahu, dia harus kuat. Demi Kinanti. Demi keluarganya.
Namun, tubuhnya terlalu lemah menahan beban pikiran yang terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan Kinanti yang hilang menyergapnya. Tubuhnya semakin lunglai, kesadarannya memudar, dan sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi, dunia di sekelilingnya menggelap. Ning jatuh pingsan.
*****
Hari berlalu. Tidak ada kabar. Tidak ada jejak. Hanya kesunyian yang semakin mencekam.
Ning semakin lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Dia lebih sering terbaring, terbangun hanya untuk menatap langit-langit kosong sambil menahan isak tangis yang tak lagi memiliki tenaga untuk keluar.
Di tempat lain, Kinan berdiri di depan meja pegawai tata usaha sekolah, tangannya mengepal erat.
“Saya ayah Kinanti,” katanya, suaranya sedikit bergetar. “Anak saya tidak pulang ke rumah sejak kemarin, dan kami belum bisa menghubunginya.”
Pegawai itu menatapnya dengan simpatik. “Baik, Pak, kami akan coba carikan informasi. Mohon bersabar sebentar, ya.”
Kinan mengangguk, tapi jantungnya berdebar semakin kencang. Waktu terus berjalan, setiap detik yang berlalu terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk kesabarannya.
Ia melangkah mendekati seorang pria yang dikenalnya sebagai Pak Amir, penjaga sekolah.
“Pak, apakah ada yang melihat Kinanti terakhir kali meninggalkan sekolah?”
Pak Amir mengerutkan kening, mencoba mengingat. “Kalau enggak salah, dia siswa terakhir yang keluar kemarin sore. Sekitar jam setengah lima.”
Jantung Kinan semakin berdegup cepat. “Ada yang mencurigakan?”
Pak Amir mengernyit, berusaha mengingat. “Hmm… kalau dipikir-pikir sih, nggak ada yang aneh. Tapi…” Ia mendadak berhenti, ekspresinya berubah. “Saya ingat ada mobil hitam mondar-mandir di depan gerbang pas jam-jam itu.”
Kinan langsung menegakkan tubuhnya. “Mobil hitam?”
Pak Amir mengangguk. “Iya, Pak. Sedan hitam. Plat nomornya saya kurang jelas lihat, soalnya agak gelap. Tapi saya yakin mobil itu bolak-balik beberapa kali, kayak lagi nunggu seseorang.”
Kinan mengernyit, pikirannya mulai menghubungkan titik-titik yang belum tersambung. “Bapak ingat jam berapa kira-kira?”
Pak Amir berpikir sejenak. “Kurang lebih jam setengah empat. Sebelum Kinanti keluar sekolah.”
Jantung Kinan berdetak lebih cepat. “Terima kasih banyak, Pak. Ini informasi yang sangat membantu.”
Sebagai jurnalis investigasi, naluri Kinan langsung bekerja. Dia sudah terbiasa menangani kasus-kasus pelik—korupsi, kriminal, dan skandal besar. Tapi kali ini, semuanya terasa lebih menyesakkan. Ini bukan sekadar berita. Ini tentang anaknya sendiri.
Tanpa membuang waktu, Kinan melajukan mobilnya ke rumah Pak Arthur, seorang kenalan lamanya. Pak Arthur adalah pensiunan polisi yang bertahun-tahun bertugas di divisi kriminal.
Dia terkenal sebagai penyidik yang cerdas dan punya insting tajam dalam mengungkap kejahatan. Setelah pensiun, Pak Arthur tetap aktif membantu kasus-kasus tertentu secara independen, menggunakan keahliannya dan jaringan luas yang masih ia miliki.
Sesampainya di sana, pria paruh baya itu menyambutnya dengan ramah.
“Silakan masuk, Kinan,” katanya, menepuk bahunya. “Duduk dulu, kita ngobrol santai aja.”
Kinan mengangguk, tapi tak bisa menyembunyikan ketegangan dalam dirinya. “Terima kasih, Pak. Saya nggak mau buang waktu. Saya butuh bantuan Bapak.”
Pak Arthur menatapnya serius. “Tentu. Ceritakan saja. Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu.”
Tanpa ragu, Kinan menceritakan semuanya—hilangnya Kinanti, kecurigaan soal mobil hitam, dan betapa pentingnya setiap petunjuk sekecil apa pun. Pak Arthur menyimak dengan seksama, sesekali mengangguk.
“Hmm… kasus ini menarik,” gumamnya setelah Kinan selesai bercerita. “Saya rasa kita perlu telusuri lebih jauh soal mobil hitam itu.”
Tanpa membuang waktu, Pak Arthur mulai mengoperasikan komputernya. Jari-jarinya lincah mengetik di keyboard, membuka folder-folder rekaman CCTV dari hari Kinanti menghilang.
“Kita mulai dari jam setengah empat,” katanya sambil menarik nafas dalam. “Semoga ada petunjuk.”
Kinan menatap layar monitor dengan saksama. Jantungnya berdegup kencang, harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu.
Detik demi detik rekaman berjalan. Mereka melihat lalu-lalang siswa keluar gerbang, beberapa guru berjalan pulang, kendaraan yang melewati jalanan depan sekolah. Semuanya terlihat biasa saja.
Sampai tiba-tiba—
“Itu dia!” seru Kinan, menunjuk layar dengan mata membelalak. “Mobil hitam!”
Pak Arthur langsung memutar ulang rekaman, memperlambat kecepatannya. Di layar, terlihat jelas sebuah sedan hitam melaju pelan di depan sekolah. Mobil itu berhenti beberapa meter dari gerbang.
Seseorang keluar dari dalam mobil. Sosoknya samar-samar, memakai jaket dan topi. Dia berdiri sejenak, lalu…
Kinan menahan napas.
Orang itu melangkah masuk ke dalam gerbang sekolah.
Pak Arthur menyipitkan mata, insting penyidiknya langsung aktif. “Lihat cara dia bergerak,” katanya lirih. “Itu bukan gerakan orang biasa. Saya pernah melihat pola seperti ini dalam kasus penculikan.”
Kinan menoleh, sorot matanya semakin tajam.
Mereka tahu, ini bukan kebetulan.
Mobil hitam itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya Kinanti.
Kinan dan Pak Arthur saling pandang, wajah mereka diliputi ketegangan. Mereka tahu, ini bukan kebetulan. Mobil hitam itu pasti ada hubungannya dengan hilangnya Kinanti.
“Kita harus cari tahu siapa orang di mobil itu,” kata Kinan, suaranya bergetar menahan emosi.
Pak Arthur mengangguk, ekspresinya serius. “Kita perlu informasi lebih lanjut. Mungkin ada CCTV lain di sekitar sekolah yang bisa menangkap plat nomor atau wajah pelakunya.”
Tanpa membuang waktu, mereka kembali menelusuri rekaman CCTV dengan lebih teliti. Kinan menatap layar monitor tanpa berkedip, berharap ada petunjuk lain yang bisa membawa mereka lebih dekat pada jawaban.
Tiba-tiba, Pak Arthur bersuara, nada suaranya berubah. “Kinan, kasus ini mengingatkan saya pada kasus lima tahun lalu.”
Kinan menoleh cepat. “Maksudnya, Pak?”
Pak Arthur menarik napas dalam, matanya menatap layar dengan penuh kewaspadaan. “Dulu, ada beberapa kasus penculikan anak di kota ini. Modus operandinya mirip dengan kasus Kinanti. Korban diincar dari sekolah, lalu diculik menggunakan mobil.”
Darah Kinan berdesir. “Lalu… anak-anak itu diculik untuk apa?”
Pak Arthur menggeleng pelan, ekspresinya suram. “Motifnya belum pernah benar-benar terungkap. Beberapa korban ditemukan… dalam kondisi mengenaskan.”
Kinan merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Bayangan Kinanti dalam bahaya terus menghantuinya. Tidak! Dia harus menemukannya. Secepat mungkin.
*****
Kinan dan Pak Arthur tak henti-hentinya menelusuri rekaman CCTV lain, mendatangi berbagai titik di sekitar sekolah, mencari kemungkinan saksi yang bisa memberi mereka informasi tentang mobil hitam itu.
Namun, semakin banyak mereka mencari, semakin tipis harapan yang tersisa.
Setiap hari tanpa kabar Kinanti terasa seperti pedang yang menggores dada Kinan. Tapi dia tidak bisa berhenti. Dia tidak boleh berhenti.
Di sisi lain, Ning mengamati usaha Kinan dengan hati yang berat. Ia tahu suaminya sedang berjuang sekuat tenaga, meskipun batinnya pasti hancur. Ning ingin membantu lebih banyak, tapi tubuhnya lemah, pikirannya kacau, dan setiap kali ia mencoba untuk tegar, bayangan putrinya yang hilang kembali menyiksanya.
Satu-satunya yang bisa Ning lakukan adalah berdoa.
“Ya Tuhan… tolong lindungi Kinanti. Kumohon… kembalikan dia pada kami…”
Sementara itu, di tempat lain, Kinan masih terus bergerak.
Ia memeriksa setiap rekaman, mendatangi orang-orang, menelusuri rute yang mungkin dilalui mobil hitam itu. Setiap informasi sekecil apa pun menjadi sangat berarti.
Dia tidak akan berhenti sampai Kinanti ditemukan.
Hanya satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya.
Nanti… di mana kamu?
*****
Kinan menelusuri peta rute yang biasa dilalui mobil hitam. Matanya terpaku pada sebuah titik yang menarik—sebuah rumah besar, tersembunyi di balik tembok tinggi.
“Rumah ini terlihat mencurigakan,” gumamnya, alisnya mengernyit. “Mungkin ada hubungannya dengan kasus penculikan.”
Hatinya berdebar lebih kencang. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. Naluri investigasinya menyuruhnya untuk menggali lebih dalam. Siapa pemilik rumah itu? Apa yang disembunyikan di balik tembok tinggi itu?
Kinan makin yakin. Ini bisa jadi titik balik dalam pencarian Kinanti.
Malam itu, dengan napas tertahan, dia bersembunyi di balik semak-semak, menatap rumah besar itu. Lampu-lampunya masih menyala, tapi suasana begitu sunyi. Tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan.
Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan.
Dengan hati-hati, Kinan merayap mendekati pagar tinggi. Tangannya menyentuh permukaan besi yang dingin, lalu matanya menangkap sebuah celah kecil di pagar. Cukup untuk dimasuki.
Dengan susah payah, dia menyelinap ke dalam halaman. Udara malam terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Namun, bukan itu yang membuatnya menggigil. Ada sesuatu di tempat ini—sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat salah.
Kinan meraba-raba dinding, mencari pintu masuk. Tangannya menyentuh sebuah pegangan pintu tua. Perlahan, ia memutarnya, pintu itu terbuka sedikit—cukup untuknya mengintip ke dalam.
Ruangan besar dengan penataan mewah menyambutnya. Lampu remang-remang menerangi interior megah itu. Namun, mata Kinan segera tertuju pada sesuatu yang lain—sekelompok orang duduk melingkar di lantai.
Dia menahan napas.
“Dia sudah sampai juga,” suara berat seseorang menggema di dalam ruangan.
Kinan tersentak. Dia hampir saja ketahuan! Dengan cepat, dia menyelinap ke balik pintu, tubuhnya menegang.
“Tugasmu sudah selesai. Sekarang tinggal menikmati hasilnya,” suara lain terdengar, nadanya penuh kepuasan.
Kinan mengerutkan kening. Hasil? Maksudnya apa?
Lalu, suara lain menyusul, lebih tajam. “Jangan lupa, besok kita kirim paket terakhir.”
Paket?
Tiba-tiba, hawa dingin menyergap tubuhnya.
Jangan-jangan…
Jangan-jangan Kinanti…
Darahnya membeku.
Kinan ingin bergerak, ingin berlari ke dalam ruangan itu dan menuntut jawaban. Tapi kakinya tak bisa digerakkan. Seolah tubuhnya terkunci dalam ketakutan yang mencekik.
Lalu—
BRRRRRR!!!
Suara dering telepon menusuk telinganya.
Kinan tersentak. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dadanya naik-turun, matanya masih liar mencari rumah besar itu—tapi yang ada hanya kegelapan di sekelilingnya.
Dia butuh beberapa detik untuk menyadari di mana dirinya.
Bukan di dalam rumah itu. Bukan di dalam mimpi mengerikan itu.
Tapi di dalam mobilnya, terparkir di sisi jalan raya yang sepi, dengan hujan deras mengguyur kaca depan. Lampu-lampu kota yang redup memantulkan bayangan gemetar di permukaan basah, membuat suasana semakin suram.
Tangannya meremas setir, berusaha mengendalikan detak jantung yang masih berdegup kencang.
Hanya mimpi.
Tapi begitu nyata. Begitu terasa. Seakan bukan sekadar bunga tidur, melainkan peringatan.
Dering telepon masih menggema di kabin mobil, menembus suara hujan yang terus menderu.
Dengan tangan gemetar, Kinan meraihnya.
“Halo?” suaranya parau.
Di ujung sana, suara berat yang tak asing terdengar.
Suara yang dipenuhi harap, ketakutan, dan kecemasan.
Ning: “Halo, Kinan…”
Kinan menghela napas, mencoba meredakan gemuruh di dadanya. Suaranya terdengar berat, sedikit terputus oleh suara hujan yang menghantam kaca mobil.
Kinan: “Halo, Ning…”
Ning: (Suara Ning terdengar lebih tenang, tapi tetap penuh kekhawatiran.) “Kinan… kamu masih di sana?”
Kinan: (Matanya masih fokus pada jalanan yang basah dan licin.) “Iya, Ning, aku masih di sini”.
Ning: “Aku nggak bisa berhenti mikirin Nanti…” (Suaranya mulai bergetar lagi.) “Gimana kalau sesuatu terjadi sama dia? Gimana kalau kita terlambat?”
Kinan: “Ning…” (Menarik napas dalam, mencoba meredam emosinya.) “Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Kita harus percaya kalau Nanti baik-baik saja. Aku akan menemukannya”.
Ning: “Tapi bagaimana kalau ini lebih dari sekadar pergi tanpa kabar? Bagaimana kalau”— (Ning tercekat, tak sanggup melanjutkan kalimatnya.)
Kinan mengencangkan genggamannya pada setir. Hujan semakin deras, menambah kesan mencekam pada malam yang terasa begitu panjang.
Kinan: (Suara lebih tegas) “Ning, dengarkan aku. Aku tahu kamu takut, aku juga takut. Tapi aku nggak akan berhenti sampai aku menemukan Nanti. Aku janji”.
Ning: (Mengusap air matanya, suaranya lemah.) “Aku nggak tahu harus gimana kalau sampai terjadi sesuatu sama dia, Nan… Aku nggak tahu harus gimana…”
Kinan menatap lurus ke depan, matanya tajam. Di dadanya, ketakutan bercampur dengan tekad yang membara.
Kinan: (Nada lebih lembut) “Ning, kamu harus kuat. Aku butuh kamu tetap waras di rumah. Aku nggak bisa lakukan ini sendirian. Aku butuh tahu kalau kamu masih di sana, menunggu kami pulang”.
Ning: (Menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan dirinya.) “Iya… iya, Kinan. Aku di sini. Aku akan menunggu kalian pulang”.
Kinan: “Aku tahu. Terima kasih, Ning”.
Sesaat, hanya suara hujan dan napas keduanya yang terdengar di telepon. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Hanya ketakutan yang saling mereka bagi dalam keheningan.
Ning: (Dengan suara lirih) “Kinan… aku cinta kamu,”
Kinan: (Menutup matanya sesaat, sebelum kembali fokus ke jalan.) “Aku juga cinta kamu, Ning. Selalu”.
(Telepon terputus.)
Kinan menghela napas panjang, meletakkan ponselnya di dasbor. Tangannya kembali menggenggam setir, matanya penuh tekad. Malam ini belum berakhir. Pencariannya baru saja dimulai.
*****
Ning masih memegang ponselnya erat, seolah tak rela percakapan itu berakhir. Suara Kinan masih terngiang di telinganya, tapi di kepalanya, ketakutan terus berputar seperti pusaran air yang tak berujung.
Tangannya gemetar. Perlahan, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia mencoba menahan, tapi hatinya terlalu penuh dengan kekhawatiran yang menyesakkan.
Di luar, hujan masih deras. Petir sesekali menyambar, menerangi ruangan untuk beberapa detik sebelum kegelapan kembali menyelimuti.
Ning berjalan ke jendela, menatap langit malam yang kelam. Di kejauhan, suara gemuruh hujan seperti bisikan yang tak membawa ketenangan.
“Ya Tuhan… kumohon… jaga mereka…”
Ia memejamkan mata, tangannya mengepal di dada. Ada sesuatu di dalam dirinya yang terasa rapuh, namun dia tahu dia tidak bisa menyerah.
Di tengah hujan, di antara ketakutan dan harapan, Ning hanya bisa menunggu.
*****
Hujan masih mengguyur deras ketika Kinan akhirnya tiba di depan sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak mencolok, dengan pagar besi berkarat dan lampu teras yang temaram. Namun, di sinilah titik terakhir yang ia lacak setelah menyusuri jejak Kinanti.
Kinan turun dari mobil, napasnya berat. Jantungnya berdegup kencang—antara harapan dan ketakutan bercampur dalam pikirannya.
Dia mengetuk pintu dengan tergesa-gesa. Hujan menetes dari rambutnya, membasahi jaket yang sudah lembap sejak perjalanan tadi. Tak lama kemudian, pintu terbuka perlahan.
Seorang perempuan berusia sekitar 40-an muncul di balik pintu. Wajahnya tampak ragu saat melihat Kinan yang berdiri dengan ekspresi tegang.
“Selamat malam, Bu. Maaf mengganggu… Saya Kinan, ayahnya Kinanti. Apa anak saya ada di sini?” suara Kinan terdengar sedikit bergetar, mencoba menahan gejolak di dadanya.
Wanita itu, yang ternyata ibu dari teman Kinanti, tampak terkejut sejenak. Lalu, dengan ragu, ia mengangguk pelan. “Kinanti ada di dalam, Pak. Dia datang ke sini kemarin…”
Dada Kinan langsung terasa sesak. Dia mengangguk cepat. “Saya bisa bertemu dengannya?”
Sang ibu melangkah ke dalam dan memanggil nama putrinya, lalu tak lama kemudian seorang gadis muncul dari balik pintu kamar.
Kinanti.
Untuk sesaat, Kinan merasa dunia berhenti berputar.
Gadis berusia 15 tahun itu berdiri diam di ambang pintu, wajahnya tampak lelah. Dia mengenakan kerudung yang sedikit kusut, namun tetap membingkai wajahnya yang tegas. Meskipun cantik, ekspresinya terlihat keras, mencerminkan keteguhan hatinya. Alisnya yang tertata rapi sedikit berkerut, dan sorot matanya menyiratkan ketakutan serta penyesalan.
Kinanti menundukkan pandangannya sesaat, lalu mengangkat wajahnya, menatap ayahnya dengan mata yang berkaca-kaca.
Tanpa pikir panjang, Kinan melangkah cepat dan langsung merengkuh putrinya dalam pelukannya.
“Nanti, kamu bikin Bunda sama Ayah khawatir!”
Kinanti diam saja, tubuhnya terasa kaku di pelukan ayahnya. Tapi Kinan bisa merasakan bahunya yang sedikit bergetar. Air mata mulai mengalir di pipinya, meskipun dia berusaha menahannya.
Kinan menghela napas dalam, memeluknya lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa putrinya benar-benar ada di sini, selamat.
Dia ingin marah, ingin menegur Nanti karena menghilang tanpa kabar. Tapi melihat putrinya seperti ini, hanya satu hal yang lebih kuat dari amarahnya: kelegaan.
Kinanti diam saja. Dia tidak menangis tersedu-sedu seperti anak kecil, tapi Kinan bisa melihat sorot mata putrinya yang dipenuhi penyesalan. Ada kilatan rasa bersalah di sana, namun juga sesuatu yang lain—sesuatu yang selama ini mungkin tak pernah mereka sadari.
Kinan menghela napas dan mengelus kepala Kinanti dengan lembut. “Udah, ayo kita pulang. Bunda pasti udah nungguin kamu.”
Kinanti hanya mengangguk pelan, masih diam, membiarkan Ayahnya membimbingnya keluar.
*****
Begitu pintu rumah terbuka, Ning langsung berlari menghampiri. Tatapan matanya dipenuhi air mata, mencari sosok yang selama ini ia nantikan dengan penuh doa.
Saat matanya menemukan Kinanti, ia tidak ragu sedikit pun. Dengan sekuat tenaga, Ning merengkuh putrinya dalam pelukan yang erat.
“Nanti sayang.!” suara Ning bergetar, mencerminkan betapa ia menahan rasa sakit dan takut selama ini.
Kinanti diam, membalas pelukan ibunya tanpa kata. Namun perlahan, bahunya mulai bergetar, dan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga.
Kinan berdiri di samping mereka, mengamati putrinya yang akhirnya kembali. Namun, di balik kelegaan itu, ada sesuatu yang masih mengganjal di dadanya.
Dia menarik napas dalam, lalu berbicara dengan suara yang lebih tegas. “Nanti, kamu harusnya ngasih kabar kalau mau pergi. Ayah dan Bunda khawatir setengah mati.”
Kinanti menunduk. Ia tahu dirinya salah. Ia tahu kepergiannya tanpa kabar membuat orang tuanya kalang kabut. Tapi…
Perasaan itu masih ada.
Sebuah rasa yang telah lama ia pendam.
Tiba-tiba, Kinanti melepaskan pelukan Ning dan mundur selangkah. Matanya masih berkaca-kaca, tapi kini sorotnya berubah. Lebih tegas. Lebih dalam.
“Ayah, Bunda… Nanti capek diatur-atur terus! Nanti pengen punya kehidupan sendiri!”
Suasana yang sebelumnya dipenuhi haru langsung berubah tegang.
Ning menatap putrinya dengan mata terbelalak, seolah tak percaya bahwa kata-kata itu keluar dari mulut Kinanti.
Kinan, yang tadinya mencoba tetap tenang, ikut terkejut. Namun ia tidak langsung bicara. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar emosi sesaat.
Kinanti mengusap matanya yang masih basah, lalu lanjut bicara. Suaranya sedikit bergetar, tapi tetap terdengar penuh keyakinan.
“Nanti capek diperlakukan kayak anak kecil, Bun, Yah! Nanti pengen punya kehidupan sendiri. Kalian nggak pernah percaya sama Nanti!”
Ning semakin terpukul mendengar ucapan itu. Bibirnya bergetar, air matanya yang sempat reda kini kembali mengalir.
“Nanti… Bunda cuma khawatir sama kamu…” ucapnya dengan suara lirih.
Kinanti tertawa kecil, namun getir. “Khawatir? Selama ini yang ada cuma aturan! Nanti nggak pernah dibolehin punya teman, punya kegiatan sendiri. Nanti benci diperlakukan kayak gini!”
Kinan dan Ning terdiam.
Kinan akhirnya melangkah mendekat, lalu dengan lembut memegang bahu Kinanti.
“Nanti, kita perlu ngobrolin ini baik-baik,” katanya, suaranya lebih tenang. “Tapi sekarang, Nanti sudah pulang, dan itu yang terpenting.”
Kinanti masih menatap Ayahnya dengan tatapan penuh emosi. Namun perlahan, sorot matanya melembut.
Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah menuju kamarnya.
Ning hanya bisa menatap kepergian putrinya dengan hati yang masih kacau. Sementara Kinan, meski tampak lebih tenang, tahu bahwa ini belum selesai.
Mereka telah menemukan Kinanti.
Namun ada sesuatu yang lebih besar yang kini harus mereka hadapi—jarak yang selama ini tanpa sadar tercipta di antara mereka.
Suasana di ruang tamu terasa begitu canggung setelah Kinanti masuk ke kamarnya. Ning dan Kinan saling pandang, masing-masing mencoba mencari jawaban di mata satu sama lain. Mereka tahu ini belum selesai. Ini bukan sekadar tentang Kinanti yang pergi tanpa kabar—ini tentang hubungan mereka sebagai keluarga, tentang kepercayaan yang selama ini tanpa sadar tergores.
Mereka harus menemukan cara untuk memperbaiki semuanya.
Namun sebelum mereka sempat berbicara, suara langkah kecil terdengar dari arah lain rumah.
“Kak Nanti!”
Kinari, anak ketiga mereka yang baru berusia dua belas tahun, berlari dan langsung memeluk kaki Kinanti yang baru saja keluar dari kamarnya. Gadis kecil itu menatap kakaknya dengan mata berbinar, seolah takut kalau Kinanti akan menghilang lagi.
“Aku kangen banget sama Kakak!” katanya dengan suara ceria, meskipun ada ketulusan mendalam di dalamnya.
Di sudut ruangan, Kinanda—anak sulung Kinan dan Ning yang lebih pendiam—hanya diam menatap. Ekspresinya datar seperti biasanya, tetapi Kinan mengenal putranya lebih dari siapa pun. Ada sedikit kelegaan di mata Kinanda, meskipun dia tak mengucapkan apa pun.
Kemudian, suara kecil lainnya muncul.
Kinara, si bungsu yang baru berusia lima tahun, berdiri dengan wajah bingung. Tangannya mencengkeram ujung baju Kinanti, matanya berkaca-kaca. “Kakak kenapa pergi? Aku takut…” suaranya terdengar lirih.
Kinanti menatap adik-adiknya. Ada sesuatu yang tiba-tiba menghantam hatinya. Dia pikir hanya Ayah dan Bunda yang khawatir, tapi sekarang dia melihat betapa kepergiannya telah memengaruhi saudara-saudaranya juga.
Tiba-tiba, Kinari menarik-narik baju Kinanti dengan gemetar, lalu berkata dengan suara yang sedikit tersendat. “Kakak jahat… Kakak bikin Bunda nangis!”
Suasana rumah yang tadinya sunyi mendadak jadi penuh suara. Ada tangis, ada pelukan, ada kebingungan dari si bungsu, tetapi yang pasti—ada rasa syukur karena Kinanti akhirnya kembali.
Di sisi lain ruangan, Ning menutup mulutnya, mencoba menahan emosi yang kembali menyeruak ke permukaan. Kinan menghela napas panjang, lalu merangkul istrinya, memberi isyarat bahwa mereka harus menghadapi ini bersama.
Kinanti berjongkok, meraih tangan Kinari yang kecil dan hangat. “Kakak minta maaf…” suaranya lirih, lalu tersenyum kecil. “Kakak janji nggak akan pergi lagi tanpa bilang.”
Kinari mengangguk, lalu tiba-tiba memeluk Kinanti erat-erat, diikuti Kinara yang ikut-ikutan memeluk mereka berdua.
“Kak Nanti, jangan pergi-pergi lagi!” seru Kinara, masih kegirangan.
“Iya, Kak Nanti, jangan pergi lagi ya,” timpal Kinari polos.
Kinanti tertawa kecil, matanya masih basah. “Iya, Kakak janji. Tapi kalian jangan nakal, ya.”
Kinanda yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. “Tapi jangan lama-lama pergi lagi,” katanya singkat, tapi ada ketulusan di balik kata-katanya.
Ning dan Kinan saling pandang, lalu tersenyum kecil. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai, tapi setidaknya, mereka sudah menemukan kembali pijakan untuk memperbaiki semuanya.
*****
Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, keluarga mereka duduk bersama di meja makan.
Suasana yang tadinya tegang kini dipenuhi suara sendok dan garpu beradu, canda tawa, serta kehangatan yang selama ini terasa jauh.
Kinanti bersandar di bahu Ning, Kinara duduk di pangkuan Kinan, Kinanda sibuk menyantap makanannya, dan Kinari masih sibuk memainkan sendoknya sambil sesekali mencuri pandang ke arah kakaknya.
Di tengah-tengah makan malam, Kinari tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatap Kinanti dengan mata besar yang berkaca-kaca.
“Kak Nanti, aku sayang kamu.”
Semua orang langsung berhenti makan.
Kinanti menatap adiknya, lalu tersenyum. “Aku juga sayang Kinari.”
Ning dan Kinan saling pandang, air mata bahagia mulai memenuhi pelupuk mata mereka.
Mereka tahu, ini adalah awal baru.
Sebuah awal untuk memahami satu sama lain lebih baik.
*****
Dua tahun berlalu.
Rumah keluarga Ning dan Kinan kini terasa lebih hangat. Banyak hal telah berubah sejak malam itu, ketika Kinanti akhirnya kembali. Hubungan mereka sebagai keluarga perlahan membaik, tidak lagi dipenuhi aturan yang mengekang atau kesalahpahaman yang membuat jarak. Kini, mereka lebih terbuka satu sama lain.
Kinanti yang dulu merasa dikekang, kini tumbuh menjadi gadis yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. Setelah lulus SMA, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya—melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Kebidanan.
Sore itu, Kinanti duduk di teras rumah, menikmati angin yang berembus pelan. Matanya menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Ada perasaan campur aduk di hatinya—antusiasi, gugup, dan sedikit takut meninggalkan rumah untuk pertama kalinya.
Ning keluar dari dalam rumah, membawa segelas teh hangat dan duduk di samping putrinya.
“Lagi mikirin apa, Nak?” tanyanya lembut.
Kinanti tersenyum kecil. “Nanti lagi mikirin besok, Bunda. Rasanya masih nggak percaya kalau Nanti akhirnya bakal kuliah jauh dari rumah.”
Ning mengelus rambut putrinya dengan penuh kasih sayang. “Dulu, Nanti yang paling nggak sabar pengen bebas. Sekarang malah ragu?” godanya.
Kinanti terkekeh. “Bukan ragu, sih. Cuma… sekarang Nanti sadar, Nanti bakal kangen semuanya di sini. Kangen Ayah, Bunda, Kinara, Kinari, bahkan Kak Kinanda yang sok cool itu.”
Ning tertawa pelan. “Kami juga pasti bakal kangen Nanti. Tapi Bunda bangga banget sama Nanti. Nanti udah tumbuh jadi perempuan mandiri, yang tahu apa yang Nanti mau dalam hidup.”
Kinanti menatap Bundanya dengan penuh haru. Dua tahun lalu, mereka sering berdebat. Sekarang, Ning adalah sosok yang paling mendukungnya.
“Bunda masih takut Nanti bakal hilang lagi?” tanya Kinanti pelan.
Ning menghela napas, lalu tersenyum. “Bunda nggak pernah takut kehilangan Nanti. Karena Bunda tahu, Nanti selalu tahu jalan pulang.”
Kinanti tersenyum lebar, lalu bersandar di bahu Ning, menikmati kehangatan ibunya.
Di dalam rumah, suara tawa Kinara dan Kinari terdengar nyaring. Kinanda, yang kini semakin dewasa, terlihat membantu Kinan menyiapkan makan malam.
Ning menatap keluarganya dengan penuh cinta.
Mereka telah melewati banyak rintangan, tapi kini mereka lebih kuat dari sebelumnya—sebagai keluarga yang saling mendukung, memahami, dan mencintai satu sama lain.
Dan kini, Kinanti siap menghadapi babak baru dalam hidupnya.
Kinanti menatap ke dalam rumah, melihat Kinan bercanda dengan Kinara dan Kinari, sementara Kinanda tetap dengan ekspresi tenangnya, namun sesekali melirik ke arah mereka.
Sebuah senyum terukir di wajah Kinanti.
Mungkin dulu ia merasa keluarganya tak memahami dirinya. Tapi kini, ia sadar—mereka selalu ada untuknya, sejak awal.
Kini, ia siap melangkah ke masa depan.
Namun, bagi Ning, kisahnya belum berakhir.
Kadang, musuh bukan datang dari luar. Tapi dari dalam. Dari mereka yang tersenyum kepadamu, yang menggenggam tanganmu, yang menyebut namamu dengan hangat.
Kinan pikir, dia tahu siapa yang bisa dipercaya. Tapi satu demi satu, bayangan di sekitarnya mulai menunjukkan wajah aslinya.
Satu langkah salah, segalanya runtuh. Dan saat semuanya terbakar, Kinan sadar—ini bukan tentang keadilan. Ini bukan tentang benar atau salah.
Ini tentang bertahan.
Di tengah bara yang semakin membesar, hanya satu hal yang masih tegak berdiri. Ning. Tapi api ini tak pernah benar-benar padam.
Ia terus merayap, diam, tak terlihat. Hingga suatu hari, semuanya meledak. Dan kehilangan yang lebih dalam pun dimulai.
Kinan menatap berkas di tangannya. Tangannya gemetar, napasnya berat. Nama yang tertera di sana membuat dunia di sekelilingnya runtuh.
Bukan musuh. Bukan orang asing. Tapi seseorang yang selama ini berdiri di sampingnya.
Pintu ruangan terbuka. Langkah kaki mendekat. “Kinan, ada yang ingin aku bicarakan.” Kinan mengangkat wajahnya, menatap sosok itu. Dan di matanya, pengkhianatan itu akhirnya terlihat jelas.
Ikuti kisah Ning selanjutnya di Ning 6: Bara dalam Sekam
*Kisah ini fiktif. Nama, tempat, dan peristiwa dalam cerita ini hanyalah karangan penulis semata dan tidak berhubungan dengan kejadian nyata. Jika terdapat kemiripan dengan peristiwa atau tokoh nyata, itu hanyalah kebetulan belaka.
[poll id=”4″]
Dukung Konten Berkualitas
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.
Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.