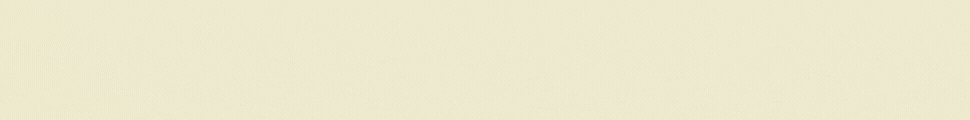“Semua karakter, peristiwa, dan lokasi dalam kisah ini adalah fiksi dan tidak memiliki hubungan dengan kejadian nyata. Penulis berharap pembaca menikmati kisah ini sebagai hiburan semata dan tidak menganggapnya sebagai fakta sejarah.”
Bab 10.2: Pewaris Panglima Hitam
Angin berhembus lembut dari arah laut, menyapu pasir putih di tepian Pulau Tidung Kecil. Ombak berdesir pelan, seolah enggan mengganggu keheningan yang menyelimuti tempat itu.
Di bawah sebuah pohon rindang yang menjulang kokoh, dua sosok terdiam, terperangkap dalam dunia ketidaksadaran yang berbeda.
Nayaka Sari duduk bersandar pada batang pohon tua, wajahnya tampak gelisah. Keningnya berkerut, napasnya tersengal, dan butiran keringat mengalir perlahan, membasahi dagu serta pipinya.
Jari-jarinya sedikit berkedut, seolah berusaha menggenggam sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang menahan jiwanya dalam pertempuran yang tak kasat mata.
Sementara itu, tak jauh darinya, Saga terdiam dengan ekspresi yang jauh berbeda. Wajahnya begitu tenang, seperti seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam dunia batinnya.
Bahkan dalam ketidaksadarannya, kulitnya memancarkan kilau samar, seperti sinar yang perlahan berpendar dari dalam dirinya.
Hasanudin berdiri tak jauh dari mereka, matanya menatap dengan cermat. Ia telah tiba beberapa saat lalu, terpanggil oleh bisikan gaib yang mengarahkannya ke tempat ini.
Kini, ia menyaksikan dua sosok yang terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada sekadar tidur biasa.
Ia berjongkok, mengamati wajah Saga dan Nayaka dengan penuh perhatian. Ada hal yang janggal—ketidakseimbangan energi antara keduanya.
Nayaka tampak terperangkap dalam bayangan ketakutan, sementara Saga tampak tenggelam dalam cahaya yang menguat.
Hasanudin menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan kanan ke arah Nayaka. Dengan lembut, ia menyentuh pundak perempuan itu, berharap bisa menariknya keluar dari mimpi yang membelenggu.
“Nayaka…” suaranya dalam, penuh ketenangan. “Bangunlah… Kegelapan tidak boleh menguasaimu.”
Namun, tubuh Nayaka tiba-tiba bergetar. Jemarinya mencengkram pasir dengan kuat, sementara bibirnya bergerak tanpa suara, seakan ingin mengatakan sesuatu namun tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat.
Saga, di sisi lain, masih diam. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, seolah ada energi yang melindunginya dari gangguan yang melanda Nayaka.
Hasanudin menoleh ke arahnya, mata tajamnya menangkap sesuatu yang unik—kilau cahaya itu bukan sekadar pantulan sinar matahari, tapi berasal dari dalam tubuhnya, dari sesuatu yang lebih dalam lagi.
Ia bergumam pelan, menyadari satu hal. Perbedaan mereka bukan hanya dalam keadaan fisik, tetapi juga dalam perjalanan batin mereka.
Nayaka masih bertarung melawan bayangan yang tersisa dalam jiwanya, sementara Saga telah menemukan sebagian dari jawabannya—sesuatu yang membuat dirinya semakin bersinar.
Hasanudin tahu ia harus bertindak cepat. Ia meraih botol kecil dari kantong kain yang tergantung di pinggangnya, membuka tutupnya, lalu meneteskan satu tetes cairan ke telapak tangannya. Aroma menyengat menyeruak, bercampur dengan udara laut yang segar.
Dengan hati-hati, ia mengusap cairan itu ke kening Nayaka, lalu membisikkan doa dengan suara perlahan.
Seperti disentak oleh kekuatan tak terlihat, tubuh Nayaka tiba-tiba tersentak. Matanya terbuka lebar, napasnya memburu, seolah baru saja keluar dari kedalaman yang gelap. Ia menoleh cepat, mencari arah, sebelum tatapannya jatuh pada Hasanudin.
Hasanudin menghela napas, memandangi Nayaka yang masih terdiam. Ia tahu ada sesuatu yang berat dalam ingatannya—dan ia hanya bisa menunggu sampai Nayaka sendiri siap berbicara
“Hasanudin…?” suaranya lirih, penuh kebingungan.
Pria itu tersenyum tipis, lalu mengangguk. “Kau kembali, Nayaka. Kau telah melewati ujian batinmu.”
Nayaka masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi ketika Saga tiba-tiba menarik napas panjang, matanya perlahan terbuka. Cahaya dari tubuhnya memudar, berganti dengan ekspresi yang damai dan penuh kewaspadaan.
Ia menatap Hasanudin, lalu beralih ke Nayaka, menyadari bahwa sesuatu telah berubah dalam diri mereka.
Hasanudin berdiri, lalu menatap mereka berdua dengan penuh harapan. “Kalian telah melewati batas yang tak semua orang bisa lewati. Tapi perjalanan ini belum selesai. Pulau Tidung Kecil menyimpan lebih banyak rahasia… dan kalian harus siap untuk menghadapinya.”
Saga dan Nayaka saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka baru saja melewati sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketidaksadaran.
Di kejauhan, awan perlahan berarak, menyibak cahaya senja yang mulai merayap di ufuk barat. Pulau ini masih menyimpan misterinya—dan mereka harus siap mengungkapnya.
*****
Nayaka masih separuh sadar, pikirannya berusaha merangkai potongan bayangan yang baru saja muncul dalam ketidaksadarannya. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak di kepalanya, seakan ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam lorong waktu yang belum sepenuhnya ia pahami.
Bayangan itu bermula…
Di tengah taman bermain yang penuh warna, suara tawa anak-anak menggema, bercampur dengan aroma bunga yang terlalu manis—terlalu sempurna. Udara terasa lebih hangat dari seharusnya, sinar matahari menyelimuti tempat itu dengan kilau keemasan yang hampir menyilaukan.
Nayaka berdiri mematung, matanya tertuju pada keluarga kecil yang sedang bermain di bawah pohon besar.
Raden Arya Saka mengayunkan anak perempuan kecil di atas ayunan, wajahnya penuh kebahagiaan. “Lihat dia, Larasati,” katanya sambil tersenyum.
“Anak kita ini akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat. Aku bisa melihat keberanian di matanya, bahkan sejak kecil.”
Ratu Larasati tertawa lembut, memegang tangan kecil Nayaka. “Dia bukan hanya kuat, Arya. Dia juga cerdas. Aku yakin dia akan membawa kebanggaan bagi kita, bagi keluarga kita.”
Nayaka kecil tertawa riang, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Namun, Nayaka dewasa yang menyaksikan semua ini merasa ada yang salah. Pakaian mereka, lingkungan ini, semuanya terasa asing.
“Tidak mungkin…” bisiknya, suaranya hampir tak terdengar.
Langit tiba-tiba berubah. Awan gelap menggulung, menutupi sinar matahari. Suara tawa itu memudar, digantikan oleh bisikan-bisikan yang tak jelas. Sosok lain muncul dari balik bayangan pohon. Ki Patih Suryanata.
Wajahnya dingin, matanya tajam seperti pisau. Ia berjalan mendekati keluarga kecil itu dengan langkah tenang namun penuh ancaman.
Raden Arya Saka berdiri, melindungi keluarganya. “Apa yang kau inginkan, Suryanata?” suaranya tegas, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan.
Ki Patih Suryanata tersenyum tipis, penuh kebencian. “Aku ingin apa yang seharusnya menjadi milikku. Kau dan keluargamu hanyalah penghalang.”
Ratu Larasati menarik Nayaka kecil ke pelukannya, matanya penuh ketakutan. “Jangan lakukan ini, Suryanata. Dia masih anak-anak!”
Namun, tanpa ragu, Ki Patih Suryanata menghunus pedang panjang dari balik jubahnya. Dalam sekejap, ia menyerang.
Darah memercik, melukis bunga-bunga di taman dengan warna merah pekat. Raden Arya Saka dan Ratu Larasati terjatuh, tubuh mereka tak bergerak.
Nayaka kecil menangis, suaranya menggema di seluruh taman. Ki Patih Suryanata mendekatinya, wajahnya tanpa ekspresi. Ia mengangkat botol kecil berisi cairan hitam pekat, lalu memaksa Nayaka kecil meminumnya. Anak itu meronta, namun kekuatannya tak sebanding.
Nayaka dewasa menyaksikan semuanya dengan mata terbuka lebar, tubuhnya gemetar. Ia ingin menghentikan itu semua, namun kakinya tetap terpaku di tempat. Cairan hitam itu mengalir ke tenggorokan Nayaka kecil, dan seketika, matanya tertutup.
Taman itu mulai runtuh. Pohon-pohon bunga layu, permainan anak-anak berkarat, dan tanah di bawahnya retak, menampakkan jurang gelap yang tak berdasar. Nayaka dewasa terjatuh, tubuhnya melayang ke dalam kegelapan.
Di tengah kehampaan itu, ia mendengar suara Ki Patih Suryanata, dingin dan penuh kekuasaan. “Ingatanmu adalah milikku, Nayaka. Kau tak akan pernah tahu kebenaran.”
Nayaka tersentak, matanya terbuka lebar, napasnya memburu. Dadanya naik turun, seperti baru saja keluar dari jurang yang dalam.
Keringat dingin masih mengalir di wajahnya, menyatu dengan pasir putih yang menempel di kulitnya. Dunia di sekelilingnya terasa buram—seolah-olah ia masih terjebak antara mimpi dan kenyataan.
Di hadapannya, sosok Hasanudin berjongkok, wajahnya penuh kecemasan. Ia menyentuh pundak Nayaka dengan lembut, mencoba menariknya kembali ke dunia nyata.
“Nayaka… kau baik-baik saja?” suara Hasanudin terdengar jauh, seakan berasal dari dua dunia yang berbeda.
Nayaka mengedipkan matanya berulang kali, mencoba menyelaraskan pikirannya. Namun, dalam bayangan buramnya, ia masih bisa melihat sekilas gambaran taman yang sebelumnya menyiksanya.
Ia masih bisa mendengar suara tawa kecilnya sendiri—dan jeritan pilu kedua orang tuanya.
Ia menggeleng cepat, mengusir bayangan itu. Namun, tubuhnya masih terasa berat, seakan sesuatu dari mimpi itu belum sepenuhnya pergi.
Hasanudin menghela napas, lalu meraih botol kecil dari kantongnya. “Minumlah ini, agar kau bisa benar-benar sadar.”
Nayaka meraih botol itu dengan tangan gemetar, kemudian meneguknya perlahan. Rasa pahit menyentak lidahnya, tapi setidaknya, pikirannya mulai kembali tenang.
Di sisi lain, Saga masih terdiam, wajahnya tetap memancarkan kilau aneh. Ia belum tersadar sepenuhnya—masih berada dalam dunianya sendiri.
Hasanudin menatapnya, lalu kembali menoleh ke Nayaka. “Ada apa dengan kalian berdua? Kalian terlihat seperti baru saja melewati sesuatu yang berat.”
Nayaka menggigit bibirnya, memilih diam sejenak. Namun, dalam hati, ia tahu—mimpi itu bukan sekadar ilusi biasa.
*****
Seperti halnya Nayaka, Saga yang juga masih belum sepenuhnya sadar. Dalam batas antara mimpi dan kenyataan, pikirannya kembali mengurai pengalaman yang baru saja dialaminya di dimensi yang berbeda. Bukan mimpi, bukan pula kenyataan, tetapi sesuatu yang jauh lebih nyata dari keduanya—sesuatu yang telah mengubah dirinya.
Kini, ia merasakan energi yang berbeda mengalir dalam tubuhnya, jauh lebih kuat dibanding sebelum dirinya melangkah ke dalam ruangan luas tak berbatas, tempat di mana cahaya putih menyilaukan memenuhi setiap sudut.
Udara di sekelilingnya bukanlah udara biasa—ia tidak bernapas seperti sebelumnya, tetapi merasakan kesegaran yang menyusup jauh ke dalam jiwanya, seakan menembus inti keberadaannya.
Ruangan serba putih terasa makin sunyi, seakan waktu berhenti. Saga merasakan pijakannya goyah, lalu—sekejap semuanya berubah.
Di atas, seburit sinar kuning keemasan melayang, berputar perlahan sebelum mengambil wujud sosok lelaki tua dengan pakaian putih bersih dan wajah yang memancarkan cahaya terang. Ki Cipta Buana telah hadir.
Saga hanya bisa terpaku. Sosok ini bukan manusia biasa—ia adalah pendekar legendaris yang digdaya, memiliki kesaktian yang melampaui batas manusia. Ki Cipta Buana adalah guru dari para pendekar terhebat, penjaga keseimbangan dunia persilatan.
Sejenak, ketenangan menyelimuti ruangan tak berbatas itu. Kemudian, tiga sinar lain muncul secara berurutan:
Sinar biru muda—berpendar kuat lalu berubah menjadi sosok lelaki setengah baya dengan wajah penuh karisma. Dialah Ki Jaga Baya, Ksatria Naga Samudera, murid pertama Ki Cipta Buana.
Sinar hijau—membentuk sosok lelaki berwajah oriental nan gagah. Dialah Ki Si Hun, Ksatria Naga Buana, pendekar dari negeri tirai bambu yang membawa angin timur ke dunia persilatan Nusantara.
Sinar putih keperakan—menggumpal lalu berubah menjadi pemuda gagah perkasa. Dialah Raden Arya Saka, Kesatria Naga Semesta, murid termuda Ki Cipta Buana dan pewaris jurus Tapak Naga Semesta.
Ketiga murid Ki Cipta Buana berlutut dan menyungkem, telapak tangan mereka bersatu sebagai tanda penghormatan kepada guru mereka.
Ki Jaga Baya: “Guru… setelah sekian lama, kami kembali menghadapmu.”
Ki Cipta Buana mengangguk, sinar di matanya memancarkan kebijaksanaan yang luar biasa.
Ki Cipta Buana: “Bangkitlah, murid-muridku. Hari ini bukan hari untuk mengenang masa lalu, melainkan hari untuk mengukuhkan takdir baru.”
Saga menelan ludah, matanya mengitari tiga pendekar besar yang kini berdiri di hadapan Ki Cipta Buana.
Lalu, sang guru berbalik, memandangi Saga.
Ki Cipta Buana: “Sagara, kau telah berjalan jauh. Kau telah mengarungi ujian demi ujian. Namun, perjalananmu belum berakhir. Kini, saatnya kau menerima warisan yang akan membentuk takdirmu.”
Tiba-tiba, tubuh Saga bergetar. Dari dalam dirinya, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasatmata, semua benda dan senjata pusaka yang ia miliki keluar satu per satu, melayang di udara:
Cincin Genta Buana berpendar dengan aura keemasan. Tombak Kyai Pleret berdiri tegak, memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Cemeti Bondoyono bergetar, seakan merespons perintah gaib.
Pun dengan Manik Kaca Pandita bersinar lebih terang, menyelimuti ruangan dengan energi mistis. Zirah Tameng Waja terbentuk sempurna, melindungi sang pewaris dengan kekuatan tak tertandingi. Sedangkan Buah Inti Kehidupan muncul, berpendar dengan aura suci yang menghangatkan jiwa.
Tak hanya itu, dari balik cahaya, dua sosok harimau kembar Kurnala dan Kumbala hadir—mereka mengaum, menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan kepada Saga.
Saga menatap semua ini dengan mata yang membelalak. Napasnya tercekat.
Ki Cipta Buana: “Sagara, mulai hari ini, kau adalah pewaris seluruh kesaktian Naga Semesta.”
Ki Jaga Baya, Ki Si Hun, dan Raden Arya Saka bersamaan membentuk sikap hormat kepada Saga, menerima takdir baru yang telah ditetapkan.
Saga masih berdiri dalam keterkejutan, hingga Ki Cipta Buana kembali berbicara.
Ki Cipta Buana: “Namun, warisan ini belum lengkap. Untuk menyeimbangkan kekuatanmu, kau harus menemukan tiga pusaka terakhir,”
“Pedang Kumbang Hitam, Sabuk Darah Putih, dan Mahkota Naga Samudera. Tanpa ketiga pusaka ini, kesaktianmu belum sempurna. Pergilah, temukan, dan tuntaskan takdirmu.” tutur Ki Cipta Buana
Saga mengepalkan tangan. Ia telah menerima takdir yang lebih besar dari yang ia bayangkan.
Saga masih berdiri dengan napas yang tersengal, pikirannya masih diselimuti oleh kata-kata Ki Cipta Buana. Cahaya di ruangan tak berbatas itu perlahan berubah, berpendar dengan warna-warna yang semakin intens.
Ki Cipta Buana melangkah maju, matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. “Kini, saatnya kesaktian para Ksatria Naga berpadu dalam dirimu.”
Ketiga muridnya—Ki Jaga Baya, Ki Si Hun, dan Raden Arya Saka—mengangguk bersamaan, lalu bersujud satu per satu, menunjukkan penghormatan terakhir sebelum mereka kembali ke dimensi yang lebih tinggi.
Lalu, tanpa peringatan, tubuh Ki Cipta Buana mulai berpendar kembali menjadi sinar emas, semakin terang hingga tak lagi berbentuk manusia. Ki Jaga Baya berubah menjadi sinar biru, Ki Si Hun menjadi hijau, dan Raden Arya Saka menjadi putih keperakan.
Dalam satu gerakan serempak, mereka melayang ke udara, membentuk spiral energi yang berputar di atas kepala Saga.
Saga menatap cahaya-cahaya itu dengan mata membelalak. Energi yang maha dahsyat mulai menyatu, turun perlahan seperti gelombang kekuatan yang tidak bisa ditolak.
Lalu… pusaka dan benda sakti yang selama ini ia miliki mulai berpendar:
Cincin Genta Buana bergetar liar, cahayanya bersatu dengan spiral energi para Ksatria Naga. Tombak Kyai Pleret melayang tinggi, ujungnya mengeluarkan aura panas yang berdenyut kuat.
Cemeti Bondoyono melingkar di udara, berkilau seperti kilat yang siap menghantam lawan. Manik Kaca Pandita mengeluarkan cahaya hijau mistis, seolah merespons kehadiran sang pewaris.
Sementara Zirah Tameng Waja melayang, berpendar seperti perisai tak tergoyahkan. Buah Inti Kehidupan mengeluarkan gelombang energi yang menghangatkan udara di sekitar.
Tidak hanya itu—Harimau Kembar Kurnala dan Kumbala mengaum dengan suara yang menggetarkan dimensi. Mata mereka menyala dengan warna emas, seakan mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi.
Dan lalu—dalam satu hentakan, seluruh benda pusaka dan dua harimau kembar melesat bersamaan, masuk ke dalam tubuh Saga dengan kekuatan yang luar biasa.
Tubuh Saga bergetar hebat, matanya terbuka lebar, seluruh sarafnya terasa menyala. Ia merasakan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah tubuhnya meledak dengan daya yang sulit dijelaskan.
Gelombang energi menyelimuti dirinya, membentuk aura naga yang berputar di sekelilingnya. Ia merasakan kekuatan baru mengalir di nadinya, seolah semua ilmu dan kesaktian telah terpatri dalam tubuhnya.
Ki Cipta Buana—yang kini hanya berupa cahaya emas terakhir—berbicara dengan suara yang bergema.
“Kini, kau bukan hanya seorang pendekar… Kau adalah Ksatria Naga Semesta yang terakhir. Pergilah, Saga. Takdirmu telah menunggu di luar sana.”
Tubuh Saga bergetar hebat, seakan seluruh sarafnya dipenuhi gelombang energi yang tak terlukiskan. Cahaya dari pusaka-pusaka yang baru saja menyatu ke dalam dirinya masih berpendar samar, seolah menandai kelahiran kekuatan yang baru.
Namun, di tengah gejolak itu, ia perlahan mulai merasakan keseimbangan. Nafasnya kembali teratur, dan matanya terbuka dengan kilatan berbeda—seakan ia bukan lagi Saga yang dulu.
Udara malam terasa lebih segar, angin laut berhembus lembut, membawa aroma asin yang bercampur dengan ketenangan. Dalam pandangan buramnya, ia melihat sosok yang tengah berjongkok di hadapannya. Hasanudin.
Saga mengerjap beberapa kali, mencoba menyelaraskan pikirannya dengan kenyataan. Ia telah kembali.
Hasanudin menatapnya penuh rasa ingin tahu. Ada keheranan yang jelas tergambar di wajahnya, tetapi juga ada rasa hormat yang tidak ia ucapkan.
“Kau akhirnya bangun…” suara Hasanudin pelan, namun mengandung nada penuh makna.
Saga menarik napas panjang, merasakan sesuatu yang baru dalam dirinya. Tubuhnya lebih ringan, pikirannya lebih jernih. Ia menyadari bahwa dirinya telah berubah—bahwa dirinya kini membawa warisan dari para Ksatria Naga Semesta.
Hasanudin mengulurkan tangan, membantu Saga duduk lebih tegak. Nayaka Sari, yang masih terduduk di sampingnya, menoleh cepat begitu Saga benar-benar sadar. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap, Nayaka melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Saga.
“Kakak…” bisiknya pelan, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat.
Saga menoleh ke arah Nayaka, lalu tersenyum tipis. Matanya kini memancarkan cahaya, bukan sekadar pantulan dari bulan di langit, tetapi sesuatu yang berasal dari dalam dirinya.
Namun, sebelum mereka bisa lebih jauh memahami apa yang baru saja terjadi, Hasanudin berdeham pelan. Ia masih menatap Saga dengan penuh ketelitian.
“Apa yang kau alami, Saga? Kau tampak… berbeda.”
Saga mengusap wajahnya, lalu menatap tangannya sendiri. Ia bisa merasakan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
“Aku telah menerima warisan dari Ki Cipta Buana,” jawabnya pelan namun penuh kepastian. “Aku sekarang membawa semua kesaktian dari para Ksatria Naga Semesta.”
Hasanudin menarik napas dalam, lalu mengangguk pelan. Ia tahu, sejak awal, perjalanan Saga bukan perjalanan biasa.
Namun, mendengar langsung bahwa pemuda di hadapannya kini adalah pewaris kekuatan legendaris, tetaplah sebuah kenyataan yang sulit diterima dengan begitu saja.
Ia menatap Saga sekali lagi, lalu tersenyum samar. “Kalau begitu, perjalananmu baru saja dimulai.”
Nayaka menggenggam tangan Saga, merasakan denyut energi yang masih menyelimuti dirinya. Ia tahu, mulai dari titik ini, Saga bukan lagi sekadar seorang pengembara, tetapi orang yang akan mengubah dunia persilatan selamanya.
Angin kembali berhembus, membawa pesan dari laut yang luas. Pulau Tidung kini tidak lagi sekadar tempat persinggahan—ini adalah titik awal dari takdir yang baru.
*****
Saat kesadarannya pulih sepenuhnya, pandangan Saga langsung tertuju pada lima jasad tak bernyawa yang tergeletak tak jauh dari dirinya dan Nayaka.
Darah masih segar membasahi tanah, menghitam dalam sorot bulan yang membelah malam. Rasa dingin menusuk tubuhnya bukan hanya dari udara Pulau Tidung Kecil, tetapi dari kesadaran pahit yang baru saja menamparnya.
Mereka adalah murid-murid Ki Jagaseta, yang datang dengan satu tujuan: membalas dendam atas kematian guru mereka.
Nayaka terbatuk pelan, tubuhnya masih lemas, tetapi ia segera menangkap suasana yang mencekam. Matanya beralih ke lima tubuh tak bergerak itu, lalu ke arah sosok yang berdiri di tengah mereka, Hasanudin.
Saga memandang Hasanudin—tapi kali ini, bukan sebagai pemuda biasa, bukan sebagai pendamping yang selama ini terlihat diam dan tak banyak bertindak.
Hasanudin berdiri tegak, pakaian putihnya berlumuran darah, napasnya masih teratur, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya.
Dia bukan manusia biasa. Hasanudin-lah yang telah menghabisi mereka.
Saga bangkit perlahan, tubuhnya masih sedikit bergetar akibat pengalaman alam bawah sadarnya. Ia menatap Hasanudin, yang masih berdiri tegak, seolah tidak terpengaruh oleh peristiwa brutal yang baru saja terjadi.
“Kau…” Saga membuka suara, suaranya pelan tapi dipenuhi keheranan. “…yang melindungi kami?”
Hasanudin menghela napas, lalu mengibaskan tangannya pelan, seakan mencoba menyingkirkan noda yang masih tersisa di udara.
“Aku tidak bisa membiarkan mereka membunuh kalian.”
Nayaka masih berusaha menormalkan napasnya. “Tapi… Bagaimana bisa…?”
Saga memicingkan mata. Manik Kaca Pandita dalam bola matanya bergetar, seakan merasakan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ia menatap Hasanudin sekali lagi—dan saat itulah ia melihat apa yang selama ini tak pernah ia sadari.
Di balik kesederhanaan dan kerendahan hatinya, Hasanudin adalah pendekar yang menyembunyikan kesaktian luar biasa.
Jurus Silat Tapak Bumi. Pukulan Bayangan.
Dua kemampuan yang hanya dimiliki oleh para pendekar tingkat tinggi—namun Hasanudin selama ini memilih untuk diam, menyembunyikan kekuatannya, seakan tak ingin masuk ke dalam pusaran konflik dunia persilatan.
Saga mengatur napasnya, lalu berkata dengan nada lebih tajam. “Kau bukan pemuda biasa, bukan sekadar pendamping perjalanan kami. Kau… siapa sebenarnya?”
Hasanudin menatap Saga lama, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang tenang tapi mengandung beban sejarah yang dalam.
“Aku adalah keturunan terakhir Panglima Hitam.”
Saga dan Nayaka terdiam.
*****
Sebelum Saga dan Nayaka tersadar dari alam mimpinya. Kala itu, Sang pemilik siang masih enggan beranjak, menggantung malas di ufuk barat, seolah menunda perpisahan dengan dunia.
Angin laut yang semula berhembus tenang tiba-tiba terhenti. Udara di sekitar Hasanudin berubah, tidak lagi terasa seperti hembusan senja biasa—ada sesuatu yang lain, sesuatu yang datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh mata.
Hasanudin baru saja menambatkan perahunya di tepi pantai, mengamati ombak yang bergulung pelan. Ia menarik tali dengan gerakan mantap, mengamankan perahunya sebelum melangkah menuju daratan.
Dan saat itu terjadi—suara itu datang.
“Segera ke pohon rindang di sebelah selatan pulau. Selamatkan mereka.”
Suara perempuan, lembut namun penuh urgensi.
Hasanudin terhenti. Matanya menyapu sekeliling, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia temukan hanyalah kesunyian.
Ia mengerutkan kening. Ia tidak mengenali suara itu.
Namun sesuatu dalam dirinya bergerak, seakan ada kekuatan lain yang mendorongnya untuk mengikuti bisikan tersebut.
Ia menghela napas dalam. Ada sesuatu yang mendesak—sesuatu yang lebih besar daripada sekadar firasat.
Tanpa berpikir panjang, Hasanudin bergegas menuju pohon rindang di sebelah selatan pulau, hatinya berdebar, pikirannya dipenuhi pertanyaan—siapa yang berbicara kepadanya dari alam tak terlihat?
Senja beranjak gelap, angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang bercampur dengan jejak darah yang masih basah di tanah. Saga dan Nayaka masih tergeletak tak sadarkan diri setelah perjalanan mereka melalui alam bawah sadar.
Di antara pepohonan yang rindang, Munara, Misanta, Jiun, Dimang, dan Rojani berdiri mengitari kedua pendekar muda itu. Mata mereka penuh amarah dan dendam yang menyala.
Mereka akhirnya menemukan Saga—sosok yang telah membunuh Ki Jagaseta.
Munara menyeringai puas, menatap tubuh tak bergerak Saga. “Lihat ini, akhirnya keadilan berpihak pada kita,” katanya dengan suara penuh kemenangan.
Misanta mengangguk, jemarinya mencengkeram gagang pedangnya dengan kuat. “Tanpa kesadarannya, dia hanyalah tubuh kosong. Kita bisa menghabisinya sekarang, membalas kematian guru kita.”
Jiun, yang dari awal paling haus akan pembalasan, melangkah maju. “Tak perlu banyak bicara. Kita akhiri ini sekarang.”
Namun, sebelum mereka sempat bergerak lebih jauh—
Hasanudin muncul dari balik bayangan pepohonan!
Dengan langkah tegap dan tatapan tajam, Hasanudin berdiri di antara mereka dan Saga. Pakaian putihnya berkilau dalam remang malam, tetapi matanya tak lagi menyiratkan sosok pemuda biasa yang mereka kenal selama ini.
Dimang tersentak, menghunus senjatanya. “Siapa kau?! Jangan ikut campur!”
Hasanudin menatap mereka dengan tenang, tetapi dalam suaranya tersimpan ketegasan yang tak bisa digoyahkan. “Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh mereka.”
Munara mengangkat goloknya tinggi. “Kau ingin mati bersama mereka?!”
Hasanudin tidak menjawab dengan kata-kata—tetapi dengan tindakan. Jurus Silat Tapak Bumi!
Dalam satu hentakan kaki Hasanudin ke tanah, seluruh pasir dan bebatuan bergetar hebat. Gelombang tenaga menyapu ke arah lima murid Ki Jagaseta, membuat keseimbangan mereka terguncang!
Jiun terhuyung! Misanta hampir terjatuh! Munara menahan diri agar tetap berdiri!
Namun, sebelum mereka bisa pulih— Hasanudin melancarkan Pukulan Tapak Bayangan!
Gerakan tangan Hasanudin begitu cepat, seolah ada bayangan lain yang menyerang mereka dari berbagai arah secara bersamaan!
Munara terlempar ke belakang, menghantam batang pohon! Misanta tersungkur ke pasir! Jiun terdorong jauh, tubuhnya berguling di tanah! Dimang jatuh berlutut, napasnya memburu! Rojani mencengkeram dadanya, terkejut dengan kekuatan yang baru saja mereka rasakan!
Hasanudin berdiri di tengah mereka, tidak sedikit pun terlihat kelelahan.
Dia adalah pendekar yang selama ini menyembunyikan kesaktiannya. Dia adalah keturunan Panglima Hitam.
Saga masih tak sadarkan diri, tetapi jika dia terbangun saat ini, dia akan melihat sosok Hasanudin dengan mata yang berbeda—bukan sekadar teman perjalanan, tetapi seorang pendekar sejati yang telah menjaga mereka dari bahaya.
*****
Malam semakin pekat di sisi timur Pulau Tidung Kecil. Saga, Nayaka, dan Hasanudin berdiri di depan makam Panglima Hitam, tempat yang telah lama menyimpan pusaka legendaris yang kini menjadi tujuan mereka—Pedang Kumbang Hitam.
Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, dari dalam bayang-bayang pepohonan sesuatu bergerak.
Seekor macan kumbang hitam besar muncul dari kegelapan!
Sorot matanya kuning keemasan, tubuhnya berotot dan gagah, auranya menyelimuti udara dengan tekanan yang luar biasa. Makhluk ini bukan hewan biasa—dia adalah Khodam Pedang Kumbang Hitam, penjaga terakhir pusaka Panglima Hitam!
Macan kumbang itu menggeram, menatap Hasanudin dengan tatapan tajam.
“Aku mengenali darahmu…”
Hasanudin tetap diam, tetapi jantungnya berdegup lebih cepat. Saga dan Nayaka saling berpandangan, menyadari bahwa makhluk ini bukan sekadar penjaga biasa—dia memahami garis keturunan Hasanudin.
Macan hitam ini telah menunggu pewaris Naga Semesta untuk mengambil pedang yang selama ini dijaganya! Macan kumbang melangkah maju, aura mistisnya terasa semakin menekan.
“Aku telah menjaga pedang ini selama bertahun-tahun… Wasiat Panglima Hitam adalah menunggu seorang pemuda yang akan mengubah takdir dunia persilatan. Tetapi sebelum kau mengambilnya, kau harus membuktikan bahwa kau layak!”
Saga mengepalkan tangan. Tidak semudah itu mendapatkan pusaka terakhir ini. “Kalau begitu, tunjukkan ujianmu!”
Macan Kumbang Hitam menerkam ke arah mereka!
Saga melangkah maju, siap bertarung, tetapi Hasanudin tiba-tiba menahan tangannya.
“Ini bukan sekadar pertempuran fisik, Saga…”
Nayaka mencengkeram selendangnya, tetapi dia juga bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dalam pertempuran ini.
Macan kumbang ini mengenali Hasanudin, karena ia adalah keturunan langsung Panglima Hitam, dan ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan hanya pewaris darah—tetapi juga pewaris tanggung jawab!
“Kau adalah keturunan Panglima Hitam,” suara macan kumbang bergetar seperti gemuruh. “Tapi apakah kau benar-benar pantas mewarisi warisan ini?”
Pertempuran pun dimulai!
Tapi… sebelum pukulan pertama benar-benar terjadi—Manik Kaca Pandita dalam mata Saga bergetar! Saga tiba-tiba melihat kilasan masa lalu—Ki Cipta Buana, Panglima Hitam, dan sejarah yang telah lama tersembunyi!
Darah membasahi tanah dalam perang besar! Ki Cipta Buana berdiri kokoh, di sisi kanannya, Panglima Hitam berlutut, setia sebagai pengawal terakhir!
Saga akhirnya mengerti… Panglima Hitam bukan hanya penjaga pedang ini, tetapi juga pengawal Ki Cipta Buana yang terakhir!
Saga tersentak. Dia akhirnya memahami wasiat yang ditinggalkan. Saga menatap Hasanudin, melihat keraguan dalam sorot matanya. ‘Aku tahu ini bukan sekadar pertempuran, Hasanudin. Tapi apa yang sebenarnya kau takutkan?’
Hasanudin menghela napas, matanya menatap pusaka yang telah lama dijaga keturunannya. ‘Bukan pertempurannya… tetapi jawabannya.’
Tetapi sebelum dia bisa mengungkapkan pemahamannya—macan kumbang menerjang!
Udara meledak, pasir beterbangan, dan Saga merasakan desakan besar yang membuat tubuhnya mundur beberapa langkah. Hasanudin berdiri kokoh, namun matanya tak bisa menyembunyikan getaran kecil—ujian terakhir kini ada di hadapannya, dan tak ada jalan mundur.
Macan kumbang hitam menggeram semakin keras, seakan malam itu sendiri bergetar dalam tekanan aura mistisnya.
Dan sebelum Saga bisa berkata—bayangan hitam di belakangnya bergerak. Bukan hanya macan kumbang. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih dalam, lebih mengancam.
Bagaimanakah Saga akan menghadapi ujian terakhir untuk mendapatkan Pedang Kumbang Hitam? Hasanudin harus membuktikan bahwa garis keturunannya bukan hanya warisan darah, tetapi juga warisan tanggung jawab!
Apakah Saga mampu mendapatkan Pedang Kumbang Hitam…?Ikuti kisah selanjutnya di Bab 11: Amarah di Pantai Perawan!
Dukung Konten Berkualitas
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.
Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.