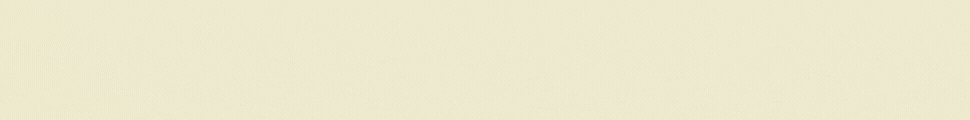“Semua karakter, peristiwa, dan lokasi dalam kisah ini adalah fiksi dan tidak memiliki hubungan dengan kejadian nyata. Penulis berharap pembaca menikmati kisah ini sebagai hiburan semata dan tidak menganggapnya sebagai fakta sejarah.”
Pelabuhan Angin Timur
BAB 12.0
Angin laut dari selatan berhembus ganas, menyapu rimbun hutan bambu di pesisir Tiongkok Selatan. Desir daun yang biasanya bernada damai kini berubah menjadi ritme kematian, mengiringi langkah seorang pemuda yang berlari terseok menembus kabut senja.
Dialah Li Si Hun, murid pilihan yang kini menjadi buronan Perguruan Awan Berlari. Pakaian putihnya koyak dan ternoda darah—darahnya sendiri, dan darah para pengkhianat yang mencoba menjatuhkannya. Ia berlari bukan karena takut, melainkan karena tahu: melawan lima seniornya di bawah segel Qi adalah langkah menuju liang kubur.
Ilmu Awan Menyapu Ombak miliknya, yang biasanya mengalir seperti air, kini berat dan tertatih, menahan tetapi tak mampu membalas.
“Li Si Hun! Berhenti berlari seperti kelinci kotor yang takut pada bayangannya!”
Suara itu menggema dari Pang Wēi, pemimpin Lima Bayangan Ular, wajahnya bagai pualam beku dengan senyum dingin penuh kemenangan. Di belakangnya, Chén Lì, si raksasa bertangan besi, menghancurkan batang-batang bambu tanpa ampun, menghina ajaran perguruan yang menjunjung harmoni dan kelembutan.
Li Si Hun tersentak ketika tusukan tajam menusuk punggungnya—cambuk rantai milik Zhōu Qín melesat seperti ular perak. Rantai itu tak mengenainya langsung, tapi hempasan anginnya mencabik kulit lengannya hingga darah menyembur. Ia jatuh, terguling di tanah yang keras dan berdebu.
“Kau tahu, Si Hun,” ujar Pang Wēi sambil mendekat perlahan, “Seandainya kau menyerah sejak awal, mungkin kami hanya akan mematahkan tubuhmu. Tapi karena kau memilih lari—kami akan mematahkan jiwamu.”
Li Si Hun berusaha berdiri. Ia menarik napas panjang, tubuhnya gemetar, tapi mata hitamnya tetap menatap tajam seperti baja yang belum patah. Taichi Aliran Murni mengajarkan lentur tanpa kehilangan bentuk—bambu bisa membungkuk, tapi tak pernah patah.
Dengan sisa Qi yang tersisa, ia menekan tanah dengan Telapak Awan.
Fuuuuusshhh!
Ledakan debu menyelimuti hutan, membuat pandangan musuhnya kabur. Dalam kekacauan itu, Si Hun melompat ke belakang batu karang besar di tepi pantai. Laut bergemuruh, ombak memercik di bawah langit jingga.
Namun nasib belum berpihak. Dari sisi lain batu itu, muncul Sūn Yǔ, si licik pembisik racun fitnah. Belatinya berkilat saat menyambar.
Sreett!
Ujung belati hanya menggores pelipis Si Hun, tapi cukup untuk membuat darah menetes di matanya. Ia setengah buta, namun tetap berdiri.
“Tamat riwayatmu, adik seperguruan!” teriak Chén Lì, tangannya mengangkat batu besar seolah hendak memecah langit.
Lalu, aroma samar menyeruak di udara. Hè Bīng, sang ahli racun, sudah melepaskan Kabut Tujuh Bunga—racun halus tanpa bau yang menembus kulit dan melumpuhkan Qi.
Udara menjadi berat. Langkah Si Hun melemah. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga jantung. Ia tahu… ini adalah akhir dari Pewaris Awan.
“Kebenaran tak pernah berpihak pada yang lemah,” bisik Pang Wēi, mengangkat tongkatnya tinggi. “Tunduklah pada takdirmu, Si Hun.”
Li Si Hun berlutut di atas pasir basah, darah dan air laut bercampur di wajahnya. Di matanya, terpantul langit yang merah membara. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya batuk bercampur darah.
Namun sebelum tongkat maut itu menghujam, angin laut berhenti. Suara ombak lenyap. Bahkan kabut racun Hè Bīng menggantung di udara, beku, tak lagi bergerak.
Lima Bayangan Ular saling berpandangan, wajah mereka pucat. Sesuatu yang tak kasat mata turun dari langit—tekanan Qi yang begitu murni hingga laut pun tunduk.
Dari ufuk barat, di mana matahari tenggelam di balik gelombang emas, sebuah kapal muncul. Bukan kapal dagang, melainkan kapal ramping bertiang tinggi, dengan panji berlukiskan ombak dan elang yang membentang melawan cahaya senja.
Di haluan kapal itu berdiri seorang kakek tua berbusana putih bersih, rambut dan janggutnya bagai salju yang diterpa cahaya api senja. Sorot matanya menembus cakrawala, tenang namun dalam seperti samudra purba.
“Hentikan kebodohan ini, anak-anak,” suaranya bergema lembut—tapi setiap kata mengguncang hati mereka seperti petir di tengah samudra. “Pertarungan yang lahir dari iri hati hanya akan meninggalkan kehancuran.”
Dan saat itulah, Ki Cipta Buana menginjakkan kakinya di pantai, langkahnya bagai ombak yang membawa penebusan. Murid-murid yang tersesat tahu, langit telah mengirimkan penghakimannya.
***
Lima Bayangan Ular—Pang Wēi, Chén Lì, Zhōu Qín, Hè Bīng, dan Sūn Yǔ—membeku di tempat. Mereka bukan takut pada Ki Cipta Buana sebagai individu, melainkan pada kekuatan yang mengendalikan alam itu sendiri. Seorang pendekar yang mampu menahan angin dan menghentikan racun di udara adalah pendekar yang berada di luar batas pemahaman mereka.
Pang Wēi, yang paling cepat pulih dari keterkejutannya, berusaha mempertahankan wibawanya.
“Siapa kau, Kakek Tua? Ini urusan internal Perguruan Awan Berlari. Jangan ikut campur!” teriaknya, meski suaranya terdengar bergetar.
Ki Cipta Buana tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggerakkan tangan kanannya perlahan, seolah sedang membelai udara. Seketika, energi yang tak terlihat memancar. Kabut Tujuh Bunga yang tadinya membeku di sekitar Li Si Hun tersapu bersih, seolah disedot oleh pusaran tak kasat mata.
Li Si Hun merasakan segel Qi di dadanya mengendur, napasnya kembali normal. Ia menatap Ki Cipta Buana dengan mata penuh keheranan dan rasa syukur yang tak terhingga.
Chén Lì melangkah maju dengan sorot mata menantang.
“Kami adalah pendekar dari aliran yang sah! Kami hanya menjalankan hukuman!”
Ki Cipta Buana menggeleng pelan, sorot matanya teduh namun penuh wibawa.
“Hukuman yang didasari iri hati adalah kehancuran. Jurus Taichi Aliran Murni sejatinya mencari harmoni, bukan dominasi. Kalian telah merusak ajaran suci Zhang Sanfeng.”
Pang Wēi menyadari bahwa mereka berhadapan dengan kekuatan yang tak dapat mereka lawan. Ia memberi isyarat kepada keempat pengikutnya untuk mundur. Namun sebelum pergi, ia meludah ke tanah, menatap Li Si Hun dengan kebencian yang membara.
“Kau beruntung hari ini, Si Hun. Tapi ini belum berakhir. Di mana pun kau bersembunyi, Lima Bayangan Ular akan menemukanmu. Kami akan memastikan takdirmu selesai!” serunya sebelum mereka lenyap di antara rimbun bambu.
Setelah mereka pergi, keheningan kembali menyelimuti pantai. Hanya suara ombak yang berdesir lembut, seolah menenangkan jiwa-jiwa yang baru saja tersentuh badai.
Ki Cipta Buana berjalan perlahan menuju Li Si Hun. Gerakannya begitu ringan, seakan ia tidak menapak tanah, melainkan melayang di atas angin. Ia berjongkok di hadapan pemuda itu yang masih bersandar lemas pada batu karang.
“Bangunlah, Nak. Luka di tubuhmu tidak seberapa dibanding luka di hatimu,” ucapnya lembut.
Li Si Hun berusaha bangkit, tapi tubuhnya goyah. Ki Cipta Buana menyentuh bahunya, dan gelombang energi hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Segel Qi yang menekan aliran tenaganya perlahan terlepas, memberi napas baru bagi jiwanya yang hampir padam.
“Aku… aku berutang nyawa padamu, Kakek Agung,” ujar Li Si Hun dengan suara serak. “Siapa Anda sebenarnya?”
Ki Cipta Buana tersenyum tenang. “Aku hanyalah pengembara dari timur jauh, dari tanah yang mereka sebut Nusantara. Namaku Ki Cipta Buana. Aku datang ke daratan ini mencari kedamaian dan menyebarkan filosofi keseimbangan.”
Ia menatap mata Li Si Hun dalam-dalam. “Aku melihat potensi luar biasa dalam dirimu, Nak. Ilmu Taichi-mu murni, tetapi jiwamu masih dibelenggu oleh dendam dan rasa sakit. Jika kau tetap di sini, kau akan terus diburu, dan pada akhirnya mati atau menjadi pembunuh yang dikuasai kebencian.”
Li Si Hun menunduk. Kata-kata itu seperti pedang lembut yang menembus dadanya, karena ia tahu semuanya benar.
“Aku tidak punya tempat lagi untuk kembali,” bisiknya lirih.
Ki Cipta Buana mengulurkan tangan, menatap ke arah laut dan kapal yang menunggu.
“Dunia ini luas, Nak. Di tanahku, di Nusantara, ada pulau-pulau yang membutuhkan penjaga. Ada lautan yang menantimu untuk menaklukkan angin. Kau adalah Angin Timur yang tersesat. Ikutlah denganku. Aku akan melatihmu untuk menyatukan ilmu Taichi, yang bersumber dari dalam, dengan Ilmu Samudera, yang bersumber dari luar. Kau akan belajar menjaga keseimbangan, bukan mengejar kekuasaan.”
Li Si Hun menatap laut yang terbentang di hadapannya, lalu kembali menatap Ki Cipta Buana. Janji tentang kehidupan baru dan takdir yang lebih besar bergetar di dadanya. Ia mengangguk pelan, menggenggam harapan yang baru lahir.
“Aku bersedia, Guru,” ucapnya, membungkuk dalam-dalam.
Ki Cipta Buana tersenyum dan menepuk bahunya dengan lembut. Keduanya kemudian berjalan menuju kapal yang berlabuh di pantai. Kapal itu tampak sunyi, seolah bergerak mengikuti kehendak sang kakek.
Sebelum kapal berlayar, Ki Cipta Buana berucap, “Mulai saat ini, kau akan meninggalkan nama Li Si Hun yang penuh luka. Di Nusantara, kau akan lahir kembali. Namamu akan menjadi Ki Si Hun—seorang ksatria yang menyatukan ilmu dari Timur dan semangat dari Buana yang agung.”
Kapal itu perlahan bergerak, membelah gelombang yang berkilau di bawah cahaya bulan. Li Si Hun berdiri di haluan, menatap siluet daratan Tiongkok yang perlahan tenggelam di balik kabut. Ia tahu, ia telah meninggalkan masa lalunya yang pahit. Di hadapannya kini terhampar lautan luas yang menjanjikan awal dari sebuah takdir baru.
Di tengah pelayaran, Ki Cipta Buana berdiri di sisi haluan, menatap ombak yang berdebur tanpa henti.
“Lautan ini, Nak,” katanya, “adalah energi yang tak terbatas. Taichi-mu mengajarimu mengambil Qi dari bumi. Di sini, kau akan belajar mengambil energi dari samudra untuk memperkuat Qi-mu. Kau akan menjadi sekuat karang, selentur angin, dan sedalam lautan. Itulah fondasi dari Ilmu Ksatria Naga Buana.”
Li Si Hun mengangguk mantap. Matanya yang semula suram kini berkilat oleh semangat baru. Ia telah meninggalkan bayangan masa lalu, dan mulai menapaki jalan menuju takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya.
***
Setelah berlayar berbulan-bulan, kapal Ki Cipta Buana akhirnya merapat di Kepulauan Seribu, tepatnya di sebuah pulau terpencil paling utara: Pulau Jagatara—yang kelak dikenal sebagai Pulau Sebira. Pulau itu tampak seperti benteng alami, dikelilingi karang tajam dan ombak ganas, seolah lautan sendiri menjaga rahasia di dalamnya agar tak tersentuh manusia.
“Selamat datang di Benteng Kanuragan,” ujar Ki Cipta Buana sambil menapakkan kaki di pasir hitam Pulau Jagatara. “Tempat ini tersembunyi dari peta para saudagar dan perompak. Di sinilah manusia ditempa menjadi penyeimbang antara dunia dan samudera.”
Begitu menjejakkan kaki, Li Si Hun—yang kini dipanggil Ki Si Hun oleh gurunya—merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di pulau itu jauh lebih asin dan liar, tetapi anehnya, aliran Qi di sekelilingnya terasa lebih murni dan tak terbatas, seolah seluruh laut menjadi satu napas kehidupan.
Di bawah naungan pohon waru laut yang menjulang, berdiri seorang pria gagah berkulit gelap terbakar matahari. Matanya tajam seperti elang, dan tubuhnya berotot seperti pahatan batu karang. Ia mengenakan pakaian dari serat kulit ikan, dan di pinggangnya terselip sebilah pedang bersarung kulit hiu. Begitu Ki Cipta Buana tiba, pria itu segera berlutut dengan penuh hormat.
“Hamba menyambut kedatangan Guru dan saudara baru,” ucapnya, suaranya berat seperti debur ombak menghantam tebing.
“Bangkitlah, Jaga Baya,” ujar Ki Cipta Buana. “Dia adalah Ki Si Hun, murid keduaku. Si Hun, kenalkan, ini Ki Jaga Baya—murid pertamaku, Ksatria Naga Samudera.”
Ki Si Hun membungkuk hormat, sementara Jaga Baya menatapnya dengan mata penuh ujian dan wibawa. Aura kekuatan dari tubuhnya berbeda—bukan Qi lembut seperti Taichi, melainkan energi mentah dari laut yang liar dan tak terduga.
Ki Jaga Baya tersenyum tipis. “Selamat datang di Nusantara, Ksatria Naga Buana. Di sini, laut adalah gurumu, dan karang adalah lawan tandingmu.”
Hari-hari di Benteng Kanuragan bukanlah hari biasa. Selama tiga bulan penuh, Ki Si Hun ditempa hingga batas jiwanya.
Ki Cipta Buana mengajarinya Pengendalian Qi Samudera, sebuah teknik untuk menyerap energi dari ombak dan udara asin. Qi internal miliknya kini mulai berpadu dengan energi eksternal laut, menjadikannya lentur seperti angin, namun kuat seperti arus pasang.
Setiap pagi, Ki Si Hun berlatih di tepi karang bersama Jaga Baya. Jurus Awan Menyapu Ombak miliknya perlahan berubah menjadi Awan Menggenggam Badai—perpaduan antara kelembutan Taichi dan kekuatan lautan. Gerakannya kini tak lagi hanya bertujuan menangkis, tetapi mampu memutar arus angin dan ombak dalam satu lintasan tangan.
Di sela pelatihan, Ki Cipta Buana menanamkan falsafahnya:
“Jadilah angin, bukan batu. Batu menghalangi, angin menghubungkan. Kau bukan pendekar dari daratan atau lautan, tetapi jembatan di antara keduanya. Itulah hakikat Ksatria Naga Buana.”
Tiga bulan berlalu. Tubuh Ki Si Hun kini kekar dan berotot, kulitnya kecokelatan, dan tatapannya setenang laut di musim teduh. Dendamnya terhadap Lima Bayangan Ular telah sirna. Yang tersisa hanyalah semangat untuk menjaga keseimbangan dunia.
Suatu pagi, di puncak tertinggi Pulau Jagatara, Ki Cipta Buana berdiri di antara dua muridnya. Dari sana, laut terbentang tanpa ujung, dan kapal-kapal dagang tampak seperti bintik di kejauhan.
“Si Hun, Jaga Baya,” ucapnya, suaranya berat dan dalam. “Waktunya kalian memahami bahwa pelatihan sejati bukan di tempat ini, melainkan di dunia luar.”
Ki Jaga Baya menunjuk ke arah selatan, ke lautan dekat Pulau Rakit Tiang—jalur dagang menuju pelabuhan besar Demak.
“Selama pelatihanmu, Tarekat Bayangan Arwah semakin berkuasa. Mereka bukan perompak biasa. Mereka menggunakan sihir hitam untuk menundukkan badai dan memerangkap kapal.”
Ki Cipta Buana menatap ke horizon. “Pemimpin mereka adalah Karmatala, penyihir bayangan yang lahir dari kerakusan laut dan manusia. Ia mengincar Batu Penyeimbang Samudera yang tersembunyi di Pulau Rakit Tiang—batu kuno yang dapat mengendalikan badai.”
Lalu, Ki Cipta Buana menatap murid mudanya dengan sorot tajam.
“Si Hun, inilah takdirmu. Pergilah ke sana. Jadilah Penjaga Gerbang Angin, dan lindungi batu itu dari tangan Karmatala. Jika ia berhasil, lautan ini akan berubah menjadi neraka abadi.”
Ki Si Hun menunduk, lalu berlutut di hadapan gurunya.
“Hamba akan melaksanakan titah Guru. Demi Buana, demi keseimbangan, hamba akan menjaga laut ini.”
Ki Jaga Baya menepuk bahunya. “Aku akan tetap di Jagatara, menjaga benteng ini. Tapi ingat, adikku—Naga Samudera selalu bersamamu, di setiap gelombang yang kau taklukkan.”
Dengan restu gurunya dan pamit dari saudara seperguruannya, Ki Si Hun menaiki kapal kecil berlayar ke selatan.
Ia tak membawa banyak bekal—hanya tekad, doa, dan ilmu yang telah menyatu dalam dirinya.
Di hadapannya terbentang laut biru, dan di kejauhan, bayangan gelap Karmatala menanti.
Takdir seorang Penjaga Angin Timur pun resmi dimulai.
***
Perahu Ki Si Hun akhirnya merapat di Pulau Rakit Tiang—sebuah pulau kecil di Kepulauan Seribu yang seolah dijaga oleh karang-karang raksasa berbentuk tiang, menjulang dari dasar laut bagaikan pasak langit. Begitu menjejakkan kaki, Ki Si Hun segera mengerti mengapa Karmatala mengincar tempat ini.
Di tengah pulau berdiri sebuah kuil batu kuno tertutup lumut. Di dalamnya tersimpan batu obsidian hitam yang memancarkan aura dingin—Batu Penyeimbang Samudera. Batu itu bukan sekadar pusaka; ia adalah penyeimbang arus dan cuaca di seluruh lautan Nusantara. Jika jatuh ke tangan yang salah, lautan bisa bergolak tanpa akhir, menenggelamkan negeri-negeri pesisir dalam badai abadi.
Ki Si Hun duduk bersila di depan kuil itu. Ia tidak membangun benteng dari batu, melainkan benteng dari energi. Dengan menggabungkan Taichi Aliran Murni dan Ilmu Samudera, ia membentangkan Jaring Energi Angin di sekitar pulau—sebuah radar gaib yang dapat merasakan setiap perubahan getaran udara.
Selain itu, ia memanggil kembali ilmu yang diajarkan Ki Cipta Buana: menciptakan Kabut Penyesat, kabut lembut yang menipu penglihatan musuh. Kabut itu menyelimuti karang di sekitar Rakit Tiang, membuat siapa pun yang datang tanpa izin akan kehilangan arah dan berputar di lautnya sendiri.
Tujuh hari tujuh malam ia berjaga dalam keheningan. Namun, pada malam kedelapan, udara berubah. Angin utara membawa aroma besi dan darah. Laut yang biasanya tenang kini bergetar. Radar angin Ki Si Hun menangkap gelombang asing—kapal-kapal besar sedang mendekat.
Pulau Rakit Tiang dihuni oleh sepuluh keluarga nelayan sederhana yang dipimpin oleh seorang tetua bernama Pak Samad. Ketika mendengar kabar dari kapal nelayan bahwa perompak dari Tarekat Bayangan Arwah tengah menuju pulau mereka, seluruh warga segera bersembunyi di gua-gua karang terdalam. Namun, tak lama setelah mereka bersembunyi, jeritan ngeri bergema dari arah pantai.
Tiga kapal hitam merapat. Puluhan perompak bertopeng turun, membawa obor dan kapak. Pemimpin mereka, Si Janggut Bara, bertubuh seperti raksasa, mengenakan mantel kulit ikan pari, dan di tangannya tergenggam kapak ganda raksasa yang berlumur garam darah. Mereka merusak rumah, membakar perahu, dan menjarah segala yang ada.
Dari balik gua, warga hanya bisa mendengar tawa bengis dan dentuman kayu yang patah. Tak ada yang berani keluar. Bagi mereka, malam itu adalah akhir dunia.
Dari balik kabut, muncul sosok Ki Si Hun. Ia berjalan menembus asap dan api, jubahnya berkibar tertiup angin laut.
“Berhenti,” serunya pelan, namun suaranya menembus malam seperti gemuruh petir yang datang dari kejauhan.
Si Janggut Bara menoleh, matanya menyipit. “Siapa bocah ini yang berani mengganggu pesta Karmatala?”
Ki Si Hun tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju, tubuhnya tenang seperti ombak yang baru lahir. Dalam sekejap, ia melompat ke depan. Jurus Awan Menggenggam Badai dilepaskan.
Tangan kirinya berputar melingkar, menangkis kapak ganda yang diayunkan ke arahnya. Dalam satu sentuhan ringan, energi Qi-nya memutar balik gaya serangan lawan. Kapak itu terlepas dari genggaman, terbang ke udara, dan menancap di batang kelapa dengan suara thunggg!
Si Janggut Bara terhuyung-huyung, kedua lengannya lumpuh. Sisa perompak mematung, tak percaya dengan apa yang mereka lihat.
Dari arah kapal utama, suara berat menggema. “Kau melukai anjingku, bocah!”
Sosok berjubah hitam melompat turun ke pantai. Tongkatnya berujung tengkorak merah menyala, memancarkan cahaya gelap seperti bara neraka. Dialah Karmatala, pemimpin Tarekat Bayangan Arwah.
“Aku adalah penguasa laut ini!” raungnya. “Aku yang menundukkan arwah perompak, badai, dan maut!”
Ki Si Hun memandangnya tanpa gentar. “Kau hanya menundukkan ketakutan. Aku adalah penjaga keseimbangan. Aku adalah Ki Si Hun—Ksatria Naga Buana. Dan lautan ini bukan milikmu.”
Karmatala meraung dan menancapkan tongkatnya ke pasir. Dari tongkat itu keluar tiga bayangan hitam, melesat cepat seperti arwah lapar—Ilmu Tiga Bayangan Hitam.
Bayangan itu menyerang dari segala arah. Namun Ki Si Hun bergerak melingkar, tubuhnya mengalir seperti air. Ia tidak melawan—ia menuntun setiap serangan, membelokkannya hingga kehilangan tenaga. Bayangan pertama lenyap. Bayangan kedua terurai menjadi kabut. Bayangan ketiga terserap ke dalam pusaran Qi di sekeliling tubuhnya.
Karmatala murka. Ia mengerahkan kekuatan penuh. Tongkat tengkoraknya menghantam bumi—muncul pusaran energi hitam yang berputar seperti badai. Ombak bergulung tinggi, seolah lautan tunduk padanya. Gema Arwah Laut dilepaskan.
Ki Si Hun menutup matanya. Ia mendengar suara laut. Ia mendengar napas gurunya. Ia mendengar jiwanya sendiri.
Lalu ia menarik dalam-dalam udara asin, membiarkan Energi Samudera mengalir menyatu dengan Qi Taichi. Ketika badai hitam itu mendekat, Ki Si Hun melepaskan jurus pamungkasnya:
Telapak Angin Murni – Membelah Samudera.
Dua gelombang Qi murni ditembakkan ke kiri dan kanan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk membelah badai itu menjadi dua. Arwah Laut Karmatala terpisah, kehilangan bentuk, lalu menguap menjadi kabut asin.
Karmatala terperanjat. Dalam sekejap itu, Ki Si Hun sudah melompat tinggi, tubuhnya berputar bagai naga yang menembus langit. Ia menghimpun seluruh Qi dari delapan arah, lalu memusatkannya ke telapak tangannya.
Pukulan itu turun, ringan seperti embun, namun membawa kekuatan yang menggetarkan bumi.
Pukulan Delapan Arah Naga.
Cahaya membuncah. Suara dentuman memecah malam.
Karmatala terlempar ke pasir, menjerit kesakitan. Tongkat tengkoraknya patah, aura hitam lenyap seketika. Ia bukan mati, namun seluruh kekuatan sihirnya hancur dan tubuhnya lumpuh tak berdaya.
Para perompak melihat pemimpin mereka tumbang. Tanpa menunggu aba-aba, mereka berlari panik ke kapal dan melarikan diri, membawa Karmatala yang pingsan. Laut menelan mereka dalam kegelapan malam.
Ki Si Hun berdiri di antara reruntuhan pantai, napasnya berat. Ombak mulai tenang. Bulan muncul perlahan di balik awan. Dari gua-gua karang, warga satu per satu keluar.
Pak Samad, sang tetua, berjalan mendekat dan berlutut. “Tuan… Anda telah menyelamatkan kami dari kegelapan. Siapa Anda sebenarnya?”
Ki Si Hun tersenyum tipis dan membantu Pak Samad berdiri. “Aku hanyalah pelaut. Aku diutus untuk menjaga keseimbangan laut ini.”
Ia menatap ke arah kuil kuno, tempat Batu Penyeimbang Samudera berdiam dalam cahaya rembulan.
Dalam diam, Ki Si Hun tahu—meski malam itu ia menang, bayangan Karmatala belum benar-benar padam. Kutukan dan dendam dari Tarekat Bayangan Arwah akan menyeberang waktu, menunggu kelahirannya kembali.
Laut pun bergemuruh pelan, seolah menyimpan janji.
***
Di Pulau Kelapa, Ki Si Hun mendirikan sebuah padepokan sederhana di tepian karang. Bangunannya tidak megah, hanya dari kayu kelapa dan batu laut, tapi dari tempat itu lahir ketenangan yang menjalar ke seluruh pulau.
Bagi para nelayan, ia hanyalah seorang Kakek Cina yang bijak, pandai membaca cuaca, dan sering menolong kapal yang hampir karam. Namun bagi mereka yang lebih peka, Ki Si Hun adalah penjaga tak kasatmata — sang Raja Tanpa Mahkota, penguasa arus dan penjaga keseimbangan laut yang tak tunduk pada kerajaan mana pun.
Tahun demi tahun berlalu. Ki Si Hun menua dalam diam. Rambutnya memutih, tapi matanya tetap jernih seperti air laut di pagi hari. Ia kini melatih cucu perempuannya, Li Hua Ni, gadis cerdas dan lincah yang tumbuh di antara dua pulau: Pulau Kelapa dan Pulau Cina.
Setiap pagi mereka berlatih di atas pasir basah — Li Hua Ni menirukan gerakan Taichi Angin Laut, sementara sang kakek mengajarkan arah angin, tanda bintang, dan rahasia arus samudera. Hingga pada suatu sore, di bawah langit jingga yang membakar cakrawala, Ki Si Hun memanggil cucunya dan mengucapkan wasiatnya:
“Li Hua Ni, cucuku.
Aku telah mengalahkan Karmatala, namun dendamnya telah menyatu dengan laut ini. Kutukannya akan menyeberang zaman, menunggu saatnya bangkit kembali.
Suatu hari nanti, Pewaris Genta Buana akan datang membawa Cincin Keemasan. Dialah harapan terakhir untuk mematahkan kutukan Karmatala dan keturunannya.
Saat waktu itu tiba, kau harus menuntunnya ke tempat rahasia di Pulau Kelapa — tempat yang hanya kau yang tahu, tempat di mana samudera menyimpan rahasianya.”
Li Hua Ni mengangguk, tapi hatinya bergetar. Angin laut meniup rambutnya, seolah laut sendiri menjadi saksi wasiat itu.
Dan beberapa tahun kemudian, ketika langit Kepulauan Seribu kembali bergolak, seorang panglima muda bernama Sagara, Pewaris Genta Buana, akan menyeberangi laut menuju Pulau Kelapa — untuk menuntaskan janji sang Ksatria Naga Buana.
Dukung Konten Berkualitas
Jika artikel ini bermanfaat bagi Anda, pertimbangkan untuk memberikan donasi melalui e-wallet.
Gunakan nomor: 082118113019 untuk melakukan donasi melalui aplikasi e-wallet pilihan Anda.